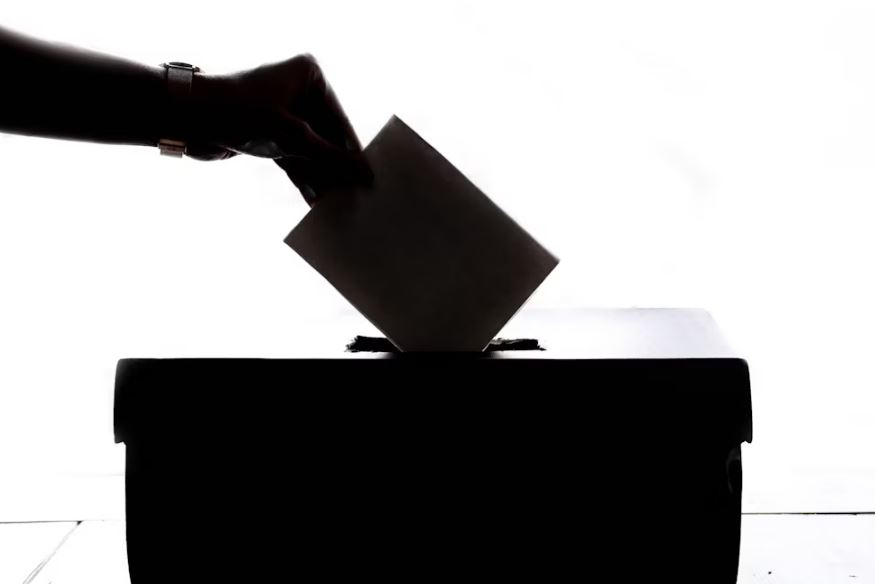Belajar Ikhlas Mengurus Persyarikatan: Teladan Sunyi dari Almarhumah Ibunda
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif (Ketua PDM Jakarta Timur)
Kepergian seseorang yang kita cintai sering kali tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga ruang perenungan. Terdapat pelajaran yang baru benar-benar terasa maknanya justru ketika sosok itu telah tiada. Begitulah yang saya rasakan ketika almarhumah ibunda saya, Hj. Endang Pudyastuti yang merupakan Bendahara Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta dan Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Jakarta Timur telah berpulang ke hadirat Allah Swt. Bagi saya pribadi, beliau bukan sekadar seorang ibu dalam arti biologis, tetapi juga guru kehidupan, teladan keikhlasan, dan potret kader persyarikatan yang bekerja dalam senyap.
Dalam dinamika gerakan Muhammadiyah, kita sering berbicara tentang amal usaha, program strategis, ekspansi kelembagaan, serta capaian-capaian organisatoris yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun, di balik semua itu, terdapat dimensi yang sering luput dari sorotan yaitu keikhlasan. Keikhlasan bukan sekadar jargon spiritual, melainkan ruh yang menghidupkan gerakan. Tanpa keikhlasan, persyarikatan bisa menjelma menjadi sekadar organisasi administratif yang kering nilai.
Ibunda saya menjalani hidup ber-Muhammadiyah dan ber-‘Aisyiyah dengan cara yang sederhana, nyaris tanpa sorotan. Tidak gemar tampil, tidak pula menjadikan amanah sebagai panggung eksistensi. Dalam banyak kesempatan, saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau memaknai pengabdian bukan sebagai jalan menuju prestise, melainkan sebagai ladang amal yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari beliaulah saya belajar bahwa mengurus persyarikatan bukan soal siapa paling terlihat, melainkan siapa paling tulus melayani.
Tulisan ini bukan sekadar memoar personal, melainkan refleksi tentang nilai keikhlasan dalam mengelola persyarikatan. Sebuah ajakan untuk kembali menempatkan etos pengabdian sebagai jantung gerakan Muhammadiyah, sebagaimana diajarkan oleh para pendahulu dan dicontohkan secara nyata oleh almarhumah ibunda.
Muhammadiyah sejak awal berdiri tidak hanya dimaksudkan sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai gerakan dakwah dan tajdid. KH. Ahmad Dahlan meletakkan fondasi bahwa Islam harus dihadirkan dalam praktik sosial: pendidikan, kesehatan, pelayanan umat, dan pembelaan terhadap kaum lemah. Karena itu, mengurus persyarikatan sejatinya adalah bagian dari ibadah sosial (‘ibadah ijtima’iyyah), bukan sekadar aktivitas organisatoris.
Namun, dalam perjalanan panjang persyarikatan, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Organisasi tumbuh besar, amal usaha berkembang pesat, struktur kelembagaan semakin birokratis. Di satu sisi, ini adalah capaian yang patut disyukuri. Di sisi lain, kompleksitas itu berpotensi menjauhkan sebagian kader dari ruh awal gerakan yaitu semangat keikhlasan dan kesederhanaan dalam berkhidmat.
Ibunda saya sering mengingatkan, “Mengurus persyarikatan itu bukan untuk mencari nama, akan tetapi untuk menunaikan amanah.” Kalimat itu terdengar sederhana, namun mengandung kedalaman makna. Amanah dalam perspektif Islam bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan, melainkan tanggung jawab moral-spiritual yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Dengan kerangka pikir semacam ini, setiap rapat, setiap kunjungan, setiap keputusan organisasi tidak lagi dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai bagian dari ibadah.
Dalam konteks Risalah Islam Berkemajuan, keikhlasan menjadi salah satu fondasi etos gerakan. Islam Berkemajuan bukan hanya tentang kemajuan institusional, melainkan kemajuan akhlak dan spiritualitas. Gerakan yang maju secara kelembagaan tetapi rapuh secara moral akan kehilangan daya transformasinya. Karena itu, keikhlasan kader dalam mengurus persyarikatan adalah modal sosial yang tak ternilai.
Sebagai Ketua PDA Jakarta Timur, almarhumah ibunda memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Daerah Jakarta Timur dengan kompleksitas sosialnya menuntut kepemimpinan yang tangguh. Namun, beliau menjalani peran itu tanpa hiruk-pikuk. Tidak banyak narasi heroik tentang dirinya, karena memang beliau tidak pernah merasa perlu membingkai pengabdiannya sebagai kisah heroisme.
Saya kerap melihat beliau seringkali berangkat pagi untuk menghadiri kegiatan ‘Aisyiyah, pulang larut setelah rapat, bahkan terkadang rapat dilanjutkan di rumah secara daring tanpa pernah mengeluh. Bahkan ketika kondisi fisik tidak selalu prima, beliau tetap berusaha hadir. Bukan karena ambisi jabatan, melainkan karena rasa tanggung jawab. Dalam diam, beliau mengajarkan bahwa kepemimpinan dalam persyarikatan adalah soal keteladanan, bukan sekadar otoritas struktural.
Kepemimpinan semacam ini selaras dengan nilai-nilai profetik yang menjadi rujukan etika gerakan Muhammadiyah yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Keempat nilai ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi perlu diwujudkan dalam praksis kepemimpinan sehari-hari. Ibunda saya mungkin tidak pernah menulis tentang konsep kepemimpinan, tetapi beliau mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.
Dalam konteks organisasi modern yang sering terjebak pada politik internal, perebutan pengaruh, atau bahkan konflik kepentingan, teladan kepemimpinan sunyi menjadi oase moral. Beliau mengingatkan kita bahwa persyarikatan tidak dibangun oleh mereka yang paling vokal mengklaim jasa, tetapi oleh mereka yang setia bekerja meski tanpa sorotan.
Keikhlasan bukan sekadar nilai individual, tetapi juga memiliki implikasi kolektif. Dalam organisasi sebesar Muhammadiyah, keikhlasan kader merupakan modal sosial yang menjaga kohesi internal. Ketika kader bekerja dengan tulus, konflik kepentingan dapat diminimalkan, trust antarstruktur terbangun, dan energi organisasi dapat diarahkan pada tujuan substantif dakwah.
Sebaliknya, ketika keikhlasan mulai tergerus oleh motif-motif pragmatis apakah berupa pencarian posisi, pengaruh, atau keuntungan simbolik, maka persyarikatan berisiko mengalami erosi moral. Konflik internal, fragmentasi kader, hingga delegitimasi kepemimpinan bisa menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.
Ibunda saya sering mengatakan bahwa ber-Muhammadiyah itu seperti menanam pohon. Kita mungkin tidak menikmati buahnya hari ini, tetapi generasi setelah kitalah yang akan memetik hasilnya. Perspektif jangka panjang semacam ini menuntut keikhlasan tingkat tinggi yaitu bekerja tanpa jaminan apresiasi langsung. Dalam dunia yang serba instan, sikap ini menjadi semakin langka, tetapi justru di situlah nilai luhur persyarikatan diuji.
Tantangan terbesar mengelola persyarikatan hari ini bukan hanya soal pendanaan, regulasi, atau sumber daya manusia, tetapi juga soal menjaga integritas nilai. Era digital menghadirkan budaya eksposur yaitu kerja baik sering diukur dari seberapa viral di media sosial. Amal saleh pun kadang tergelincir menjadi komoditas citra. Dalam konteks ini, merawat keikhlasan menjadi pekerjaan berat.
Pelajaran dari almarhumah ibunda mengingatkan kita bahwa keikhlasan perlu dirawat secara sadar. Keikhlasan bukan kondisi statis, melainkan proses spiritual yang terus-menerus diperjuangkan. Dalam tradisi tasawuf, keikhlasan adalah maqam yang sulit dicapai karena ego manusia selalu mencari pengakuan. Karena itu, kader persyarikatan perlu terus melakukan muhasabah yaitu apakah kerja-kerja kita masih murni untuk dakwah, atau telah bergeser menjadi proyek personal?
Di sinilah pentingnya penguatan ideologi dan spiritualitas kader. Pengajian, Baitul Arqam, Darul Arqam, serta forum-forum perkaderan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sejatinya bukan sekadar ruang transfer pengetahuan organisatoris, tetapi juga wahana pembentukan karakter. Keikhlasan tidak bisa diajarkan hanya melalui modul, tetapi ditumbuhkan melalui keteladanan. Teladan itu sering kali hadir dalam sosok-sosok sederhana yang bekerja tanpa banyak bicara seperti almarhumah ibunda.
Sebagai Ketua PDM Jakarta Timur, saya menyadari bahwa posisi struktural membawa tantangan tersendiri. Terdapat ekspektasi publik, tuntutan kinerja, dinamika internal yang tidak selalu mudah. Dalam situasi-situasi sulit, saya kerap teringat nasihat ibunda: “Jangan bawa perasaan pribadi dalam urusan persyarikatan. Kalau lelah, istirahatlah, tapi jangan tinggalkan amanah.”
Nasihat ini mengajarkan keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas. Mengurus persyarikatan bukan berarti mengorbankan kemanusiaan kita, tetapi juga tidak boleh menjadikan emosi pribadi sebagai penentu arah organisasi. Keikhlasan justru menuntut kedewasaan emosional yaitu mampu bekerja dengan kepala dingin, hati lapang, dan niat lurus.
Pengalaman personal ini saya harapkan dapat menjadi refleksi kolektif bagi kader Muhammadiyah di berbagai tingkatan. Bahwa di tengah tuntutan kinerja, target program, dan tekanan eksternal, kita tidak boleh kehilangan ruh pengabdian. Persyarikatan ini dibangun bukan oleh mereka yang paling kuat secara politis, tetapi oleh mereka yang paling konsisten secara moral.
Kepergian almarhumah Hj. Endang Pudyastuti meninggalkan duka mendalam, tetapi juga warisan nilai yang tak ternilai. Warisan itu bukan berupa aset material, melainkan etos keikhlasan dalam berkhidmat. Sebuah pelajaran bahwa mengurus persyarikatan adalah jalan sunyi yang menuntut ketulusan hati.
Dalam semangat Islam Berkemajuan, kita diingatkan bahwa kemajuan sejati bukan hanya diukur dari megahnya gedung amal usaha atau besarnya struktur organisasi, tetapi dari kualitas akhlak para penggeraknya. Keikhlasan adalah fondasi moral yang menjaga agar kemajuan itu tidak kehilangan arah.
Semoga kita semua, para kader persyarikatan, mampu meneladani nilai keikhlasan ini. Bekerja tanpa pamrih, melayani tanpa mengharap pujian, dan berkhidmat tanpa lelah demi tegaknya dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Semoga Allah Swt. menerima seluruh amal saleh almarhumah ibunda sebagai bagian dari amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, seiring dengan terus bergeraknya persyarikatan ini di jalan pengabdian.