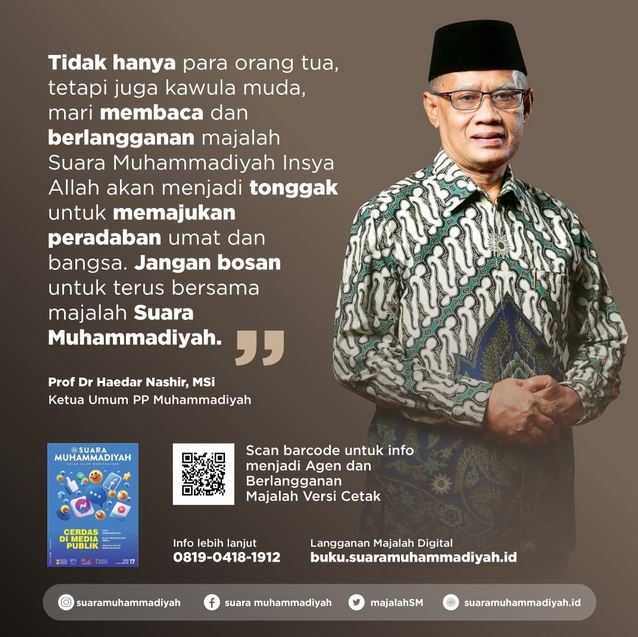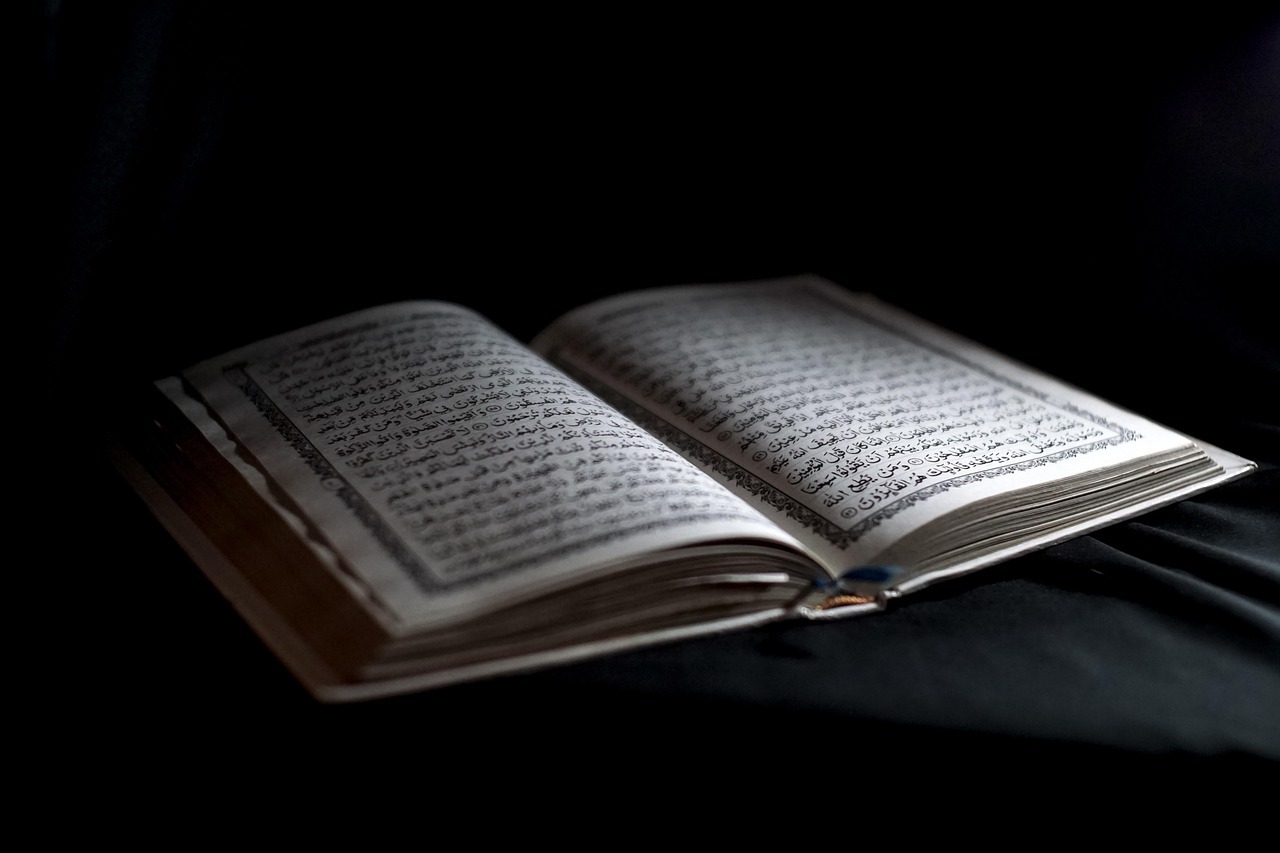Oleh: Pradana Boy ZTF, Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.
Malam itu saya mendapatkan tugas piket di sebuah hotel di kawasan Misfalah, Makkah, Arab Saudi. Hotel ini besar, meskipun tergolong tua. Halamannya tidak seberapa luas dan langsung berhadapan dengan jalan raya. Tetapi cukup untuk parkir sebuah bis dengan arah paralel.
Berbanding terbalik, ruang lobinya cukup luas, dengan keramik tua berwarna dominan krem. Sofa-sofa berwarna merah dan dihiasi lis warna emas membawa kesan mewah. Hotel itu rencananya akan ditempati 1200-an jemaah haji Indonesia. Namun malam itu baru sekitar 90-an orang yang hadir. Kedatangan jamaah memang tidak serempak, maka meskipun sudah datang tiga gelombang, baru sekitar 90-an orang yang menghuni hotel.
Ini yang membuat saya agak “menghindar” dari pengelola hotel. Karena setiap kali saya muncul untuk piket, manajer hotel selalu bertanya-tanya, “kapan jamaah yang lain akan datang?” “Katanya ada 1000 orang lebih, kenapa hanya 90 yang datang?” dan pertanyaan-pertanyaan bernada ketidaksabaran yang lain. Karena perasaan kurang nyaman dengan berondongan pertanyaan yang tak bisa saya jawab itu, saya memilih duduk di luar bersama dengan seorang staf keamanan.
Sebagai petugas, kami sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kedatangan jamaah, dan pada umumnya, kami tahu jadwal kedatangan jamaah di hari yang sama. Atau kadang beberapa jam saja.
Ada dua staf keamanan di hotel tersebut. Saya sering ngobrol dengan keduanya, melalui Bahasa Arab seadanya. Maklum, Bahasa Arab yang dulu saya pelajari adalah Bahasa Arab formal. Sehingga ketika digunakan dalam percakapan dengan orang Arab di Makkah, terasa kaku dan sulit difahami.
Jarum jam telah menunjukkan hampir tengah malam. Para jamaah sebagian terlelap dalam istirahatnya, dan sebagian berlalu-lalang untuk menunaikan umrah di Masjid al-Haram, atau sekadar belanja oleh-oleh. Saya duduk di samping staf keamanan itu. Dia pun bertanya kapan jamaah yang besar akan datang. Sebisa-bisanya, saya jelaskan. Dari tanggapannya, saya tahu itu hanya pertanyaan basa-basi pembuka percakapan.
Tiba-tiba lelaki berusia sekitar 60-an tahun itu memperkenalkan namanya. Lalu ia mengatakan: “Ana Quraisy. Arafta Quraisy?” (Saya dari Suku Quraisy. Apakah kamu tahu Quraisy?). Begitu ia bertanya kepada saya. Saya menjawab, tentu saja saya tahu, karena saya belajar tentang sejarah Islam, dan Quraisy adalah salah satu suku terkemuka di Makkah.
Dari suku inilah Nabi Muhammad berasal. Dia tersenyum, lalu mengulangi perkataannya: “Wa ana Qurasiy. Ana min ahli baiti Rasulillah” (Dan saya adalah orang Qurasiy. Saya bagian dari Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW).
Percakapan singkat jelang pergantian hari itu lalu membawa saya kepada refleksi yang lebih panjang. Quraisy, Ahlul Bait, keturunan Nabi adalah kata-kata kunci yang senantiasa menjadi bahan diskusi yang menarik. Dalam kaitan ini, belakangan, di Indonesia muncul kontroversi tentang keturunan Nabi yang lazim disebut dengan “Habib”, dan dalam bentuk jamaknya, “Habaib.”
Lazim dketahui, bahwa salah satu kelompok pembentuk masyarakat Indonesia keturunan Arab di Indonesia. Sebagian besar meraka adalah Arab Hadhrami, yakni orang Arab yang berasal dari Hadramaut atau Yaman.
Habib merujuk kepada mereka yang diyakini memiliki ketersambungan genealogi atau keturunan sampai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka sangat wajar, masyarakat Indonesia, sebuah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, menaruh penghormatan yang tinggi kepada kalangan “habaib.”
Namun, berkaitan kontroversi yang belakangan ini mengemuka di Indonesia adalah, ada kecurigaan bahwa ada kelompok tertentu yang hanya mengaku-aku sebagai keturunan Nabi demi aneka kepentingan yang bersifat duniawi.
Di Arab sendiri, dalam kaitannya dengan keturunan Nabi, istilah “sayyid” lebih populer daripada “habib.” Maka ketika saya mengambil gambar bersama petugas yang saya ceritakan di atas, dan saya unggah ke akun media sosial, segera ada yang bertanya: Apakah berarti dia Habib? Dalam menjawab pertanyaan itu, saya katakan bahwa jika yang dimaksud dengan habib adalah keturunan Nabi Muhammad, tentu saja ya. Setidaknya dari pengakuannya bahwa dia adalah min ahli baiti al-Nabiy.
Tetapi jika istilah “habib” sebagaimana yang kita gunakan di Indonesia disebutkan kepada masyarakat Arab, barangkali ada perbedaan makna sosiologis. Misalnya, di Arab Saudi, kata “habibiy” sangat sering diucapkan satu orang kepada lainnya.
Bahkan tidak jarang, seorang penjaga toko memanggil konsumennya dengan “habibiy”. Jika difahami secara harfiah mungkin ini agak janggal. Mana mungkin seorang penjaga toko memanggil pelanggannya dengan “kekasihku”.
Artinya, dalam konteks ini, antara Arab Saudi dan Indonesia ada perbedaan dalam menggunakan kata “habib.” Bahkan resepsions hotel di mana saya bertugas, jika bertanya sesuatu kepada saya, selalu diawali dengan kata: “Ya Habibi...”
Di Indonesia, kontroversi tentang keturinan Nabi ini ternyata bukan terjadi saat ini. Pada masa pra-kemerdekaan, hal itu sudah pernah terjadi. Keturunan Arab di Indonesia, pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1905, mendirikan organisasi yang bernama Jam’iatul Khair. Seorang cendekiawan Arab asal Sudan bergabung dengan organisasi itu. Tetapi tak lama setelah ia bergabung, muncullah kontroversi.
Surkati sebagai cendekiawan Muslim berfaham reformis mengajukan gagasan tentang persamaan kaum Muslimin dan menolak gagasan tentang adanya satu kelompok masyarakat lebih tinggi dari lainnya. Rupanya gagasan Surkati ini kurang disukai oleh kalangan sayyid di Hindia Belanda saat itu, lantaran dianggap bisa mengancam keberadaan kaum Alawiyin di Indonesia.
Karena gagasannya tidak mendapatkan sambutan di kalangan internal Jaim’atul Khair, Surkati akhirnya mendirikan sebuah organisasi baru, yakni al-Irsyad al-Islamiyyah yang lebih banyak dikenal dengan al-Irsyad. Dalam hal keanggotaan, al-Irsyad lebih inklusif, meskipun ada hal sensitif di dalamnya. Misalnya, al-Irsyad melarang kalangan sayyid menjadi bagian dari kepengurusan al-Irsyad.
Persoalan genealogi dan strata dalam kehidupan masyarakat adalah aspek sosiologis yang tidak bisa dihindarkan, karena memang manusia hidup dalam ruang lingkup sosial. Namun, secara teologis, Islam adalah penegak kesetaraan manusia. Haji adalah sebuah ibadah ritual yang salah satunya mengandung makna kesetaraan itu.
Sebaliknya, hal-hal yang bersifat sosiologis seperti sayyid, habib, alawi, atau yang lainnya tidak bisa kita hindari, karena setiap masyarakat punya kacamata masing-masing dalam memandang strata dalam masyarakatnya.
Akan tetapi, hendaknya yang sosiologis itu tidak mengalahkan aspek atau makna yang lebih mendasar dan universal, seperti makna teologis. Maka menghormati kalangan masyarakat tertentu atas dasar keturunannya, tentu saja tidak dilarang.
Akan tetapi ketika hal itu mengalahkan aspek universal dalam bentuk peniadaan kesetaraan, maka hal yang bersifat sosiologis itu lalu menjadi masalah. Warna putih pakaian ihram haji adalah simbol kesetaraan yang paling mendasar dan tak terbantahkan. Makkah al-Mukarramah, 21 Mei 2025.