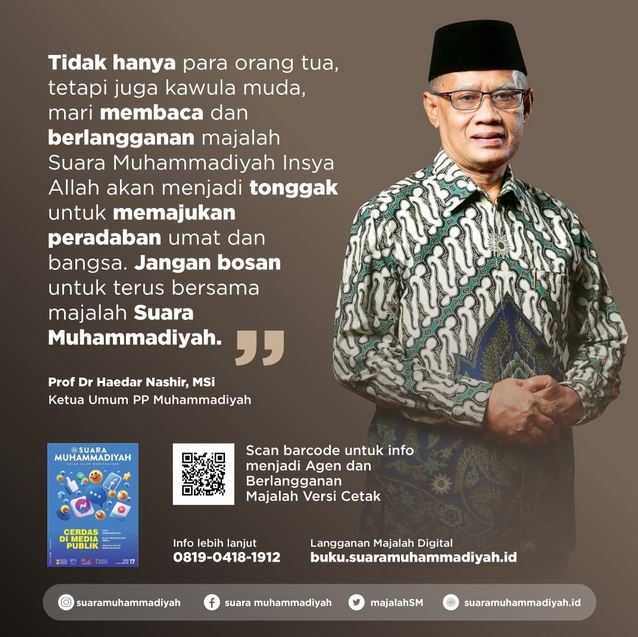YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Potensi pelanggaran dalam kebijakan karbon dinilai semakin mengkhawatirkan seiring berkembangnya perdagangan karbon nasional. Manipulasi data emisi, kredit karbon palsu, hingga praktik greenwashing disebut sebagai ancaman serius bagi integritas pasar karbon Indonesia. Kepala Prodi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Endah Saptutyningsih, S.E., M.Si., menegaskan bahwa kejahatan karbon bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga masalah ekonomi yang dapat menggagalkan tujuan penurunan emisi.
“Secara ekonomi lingkungan, kejahatan karbon itu memanipulasi pasar karbon agar seolah-olah emisi sudah dibayar. Padahal eksternalitas negatif tetap ada. Pelanggaran ini menciptakan kegagalan pasar berlapis karena emisi tetap tinggi, sementara instrumen keuangan berbasis karbon kehilangan kredibilitas,” ujar Prof. Endah, Rabu (19/11) di UMY.
Pasar karbon Indonesia saat ini berada pada fase yang sangat rentan. Karakter kredit karbon yang tidak berwujud menyebabkan banyak pihak, termasuk regulator, kesulitan menilai kualitasnya. Selain itu, harga karbon domestik yang terlalu rendah turut memperbesar potensi pelanggaran. Pada uji coba perdagangan karbon di sektor energi, harga karbon ditetapkan sekitar Rp 30.000 per ton CO₂, jauh di bawah standar harga global.
“Dengan harga rendah, insentifnya jadi tidak sehat. Aktivitas tetap bisa diklaim patuh di atas kertas, tetapi tidak memotivasi investasi rendah karbon. Situasi seperti ini sangat rentan melahirkan greenwashing,” jelasnya.
Prof. Endah menilai penguatan pengawasan pemerintah menjadi hal mendesak untuk mencegah semakin meluasnya pelanggaran. Ia mengapresiasi hadirnya Perpres No. 98/2021 sebagai payung hukum nilai ekonomi karbon (NEK), tetapi implementasinya masih membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.
“Pengawasan pasar karbon tidak bisa hanya ditumpukan pada KLHK. Unit karbon itu pada dasarnya instrumen keuangan, sehingga harus tunduk pada aturan OJK, PPATK, termasuk regulasi Anti-Money Laundering,” tegasnya.
Pemerintah juga perlu memastikan metodologi baseline yang konservatif, verifikasi independen yang kredibel, serta penindakan hukum untuk kasus manipulasi pengukuran. Platform SRN-PPI pun memerlukan standar keamanan siber yang kuat untuk mencegah sabotase data dan registri.
Menurut Prof. Endah, kerugian ekonomi yang ditimbulkan jika pelanggaran dibiarkan akan jauh lebih besar dibandingkan biaya pengawasan. Skandal kredibilitas dapat menurunkan kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pendanaan proyek hijau.
“Kalau reputasi kita jatuh, kredit karbon Indonesia bisa didiskon dan risk premium-nya naik. Itu berarti investasi hijau jadi lebih mahal,” pungkasnya.
Pengawasan Emisi dan Edukasi
Indonesia mulai memasuki fase penting dalam implementasi kebijakan karbon, seiring semakin banyaknya inisiatif transisi energi yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir sebagai pondasi menuju target pengurangan emisi jangka panjang.
Pakar Kebijakan Tata Kelola Perkotaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.IP., menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap isu karbon relatif baru menguat dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, langkah awal tersebut dinilai signifikan untuk mendorong sektor-sektor yang selama ini bertumpu pada energi fosil agar mulai beralih menuju energi bersih.
Menurut Eko, sektor transportasi publik merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar sehingga peralihannya menuju energi listrik adalah langkah yang logis. Namun, ia menekankan bahwa transisi energi tidak dapat dipahami sebagai solusi tunggal.
“Yang perlu digarisbawahi adalah bukan berarti ketika transportasi listrik berkembang, persoalan karbon langsung selesai. Setelah enam atau tujuh tahun baterai harus diganti, lalu sampah itu mau dibuang ke mana? Jangan sampai solusi karbon justru menimbulkan masalah baru,” jelas Eko.
Lebih lanjut, Eko menyebut bahwa tantangan utama kebijakan karbon tidak hanya berada pada regulasi atau teknis peralihan energi, tetapi juga pada pemahaman masyarakat.
“Bagaimana masyarakat memahami apa itu karbon, bagaimana mereka beralih dari energi fosil ke energi listrik, itu bukan hal yang ringan. Masyarakat perlu memahami dampak lanjutan seperti sampah baterai atau perangkat berbasis listrik. Jangan hanya ikut tren tanpa tahu konsekuensinya. Kesadaran itu penting,” tegasnya.
Di sektor industri, Eko menyoroti pentingnya konsistensi penegakan hukum. Meskipun regulasi terkait emisi sudah cukup ketat, pelaksanaannya dinilai belum seragam. Karena itu, pengawasan berkala sangat diperlukan untuk mencegah manipulasi data emisi.
“Ada perusahaan yang dihukum maksimal, ada juga yang tidak. Padahal kalau regulasinya bagus, penegakannya harus adil. Setiap enam bulan atau setahun juga harus ada kontrol. Tanpa evaluasi, pelanggaran bisa tidak terdeteksi,” ujarnya.
Eko menegaskan bahwa edukasi publik merupakan indikator evaluasi paling krusial dalam implementasi kebijakan karbon menuju target zero carbon 2060. Menurutnya, literasi masyarakat mengenai karbon masih perlu diperkuat agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi.
“Selain edukasi, pencarian dan pengembangan energi terbarukan juga menjadi kunci keberhasilan pengurangan emisi. Kalau edukasi masyarakat kuat, penegakan hukum konsisten, dan energi bersih terus dikembangkan, saya rasa tujuan sustainability dalam penanganan karbon bisa dicapai,” pungkasnya. (NF)