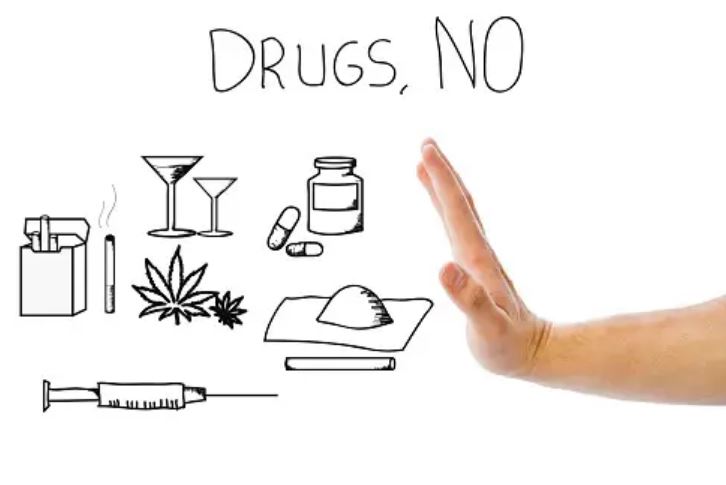Mengapa Islam Tidak Memiliki Paus?
Oleh: Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Kepergian Paus beberapa bulan lalu mengundang banyak pertanyaan tentang makna kepemimpinan spiritual. Bagi umat Katolik, Paus adalah sosok sentral: seorang pemandu rohani, otoritas global, serta simbol perdamaian dan persatuan. Namun, apakah ada figur yang setara dalam Islam?
Sebagai tanggapan, kepergian Paus disambut dengan kesedihan yang mendalam, tidak hanya oleh umat Katolik, tetapi juga oleh masyarakat dunia—khususnya umat Islam. Paus dikenang sebagai pejuang perdamaian dan keadilan yang tak kenal lelah. Ia membela hak-hak kaum miskin dan tertindas, serta vokal menyerukan perdamaian di Gaza dan penghentian perang di sana. Banyaknya kontribusi ini membuatnya akan sangat dirindukan.
Selain itu, Paus dikenal karena upayanya membangun dialog produktif antaragama. Ia berkolaborasi dengan Mufti Besar Al-Azhar untuk menulis makalah yang menyerukan diakhirinya ekstremisme. Dokumen tersebut, yang mereka tulis bersama, membela hak-hak perempuan, lansia, dan anak-anak—menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan teologis, ada banyak kesamaan nilai kemanusiaan yang mempersatukan. Kunjungannya ke Irak, di mana ia bertemu dengan para pemimpin Syiah, semakin mengukuhkan posisinya sebagai jembatan pemahaman antar keyakinan.
Sebagai seorang individu, Paus juga dinilai memiliki banyak sifat mulia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dedikasinya pada perdamaian, keadilan, dan kesetaraan menjadikannya sosok yang akan selalu dikenang. Setelah wafatnya, proses pemilihan Paus baru memunculkan pertanyaan penting bagi umat Islam: apakah ada pemimpin agama yang memiliki otoritas terpusat seperti Paus?
Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dua aliran utama dalam Islam: Sunni dan Syiah. Kelompok Sunni, yang merupakan mayoritas (sekitar 80% populasi Muslim dunia), memiliki pendekatan yang berbeda dengan Syiah, yang menyumbang sekitar 15% dari populasi global. Di antara kaum Sunni, ide kepemimpinan berakar pada pilihan rakyat. Model ini mencerminkan prinsip demokrasi, di mana pemimpin diangkat melalui suara mayoritas atau, dalam terminologi Islam, melalui bay'ah—sebuah janji setia.
Ini adalah proses yang sepenuhnya bersifat manusiawi, bukan intervensi ilahi. Pemimpin yang dipilih haruslah sosok yang teruji meritnya: saleh, taat, dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Mereka dipercaya untuk memimpin umat Islam secara global, bukan karena garis keturunan, melainkan karena kualitas dan kapabilitas mereka.
Sejarah mencatat bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang dibimbing langsung oleh Allah, kepemimpinan diteruskan kepada para khalifah yang dipilih oleh umat, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada pula khalifah lain yang memerintah setelah mereka, dengan kualitas yang bervariasi. Beberapa di antaranya, seperti Umar bin Abdul Aziz, bahkan dianggap sebagai "khalifah kelima yang dibimbing dengan benar" karena kebijakan adilnya. Mereka adalah contoh nyata dari pemimpin yang diangkat manusia berdasarkan jasa dan integritas mereka.
Namun, tradisi Syiah menawarkan pandangan yang berbeda. Mereka meyakini bahwa bimbingan ilahi tidak berakhir dengan Nabi Muhammad, melainkan diteruskan melalui keturunannya, dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin ini dikenal sebagai imam, dan mereka dianggap tidak hanya memimpin secara duniawi, tetapi juga dengan bimbingan langsung dari Tuhan. Tradisi Syiah Twelvers, yang merupakan mayoritas, meyakini keberadaan 12 imam. Imam ke-12 diyakini telah bersembunyi atau ghaib sekitar 1.000 tahun yang lalu, dan akan muncul kembali di masa depan sebagai Mahdi, atau 'yang dibimbing', untuk memimpin umat.
Saat berada di dunia, para imam Syiah memimpin tidak hanya dengan kebijaksanaan manusia, tetapi juga dengan bimbingan langsung dari Tuhan. Konsep ini memiliki kemiripan kuat dengan tradisi Katolik, di mana Paus, ketika berbicara secara resmi (ex cathedra), dianggap berbicara di bawah pengaruh dan bimbingan ilahi.
Namun, setelah imam ke-12 bersembunyi, kepemimpinan Syiah mengalami perubahan signifikan. Sejak saat itu, tidak ada lagi figur sentral yang memiliki tingkat bimbingan ilahi setara dengan para imam. Sebagai gantinya, kepemimpinan diserahkan kepada para ulama yang dikenal sebagai Ayatollah—sebuah gelar kehormatan yang berarti 'tanda Tuhan.' Meskipun Ayatollah, terutama Ayatollah Agung, memiliki otoritas yang sangat tinggi dan dihormati, mereka tetap dianggap sebagai wakil, bukan penerus langsung, dari para imam yang dibimbing secara ilahi. Mereka tidak memiliki tingkat bimbingan dan inspirasi ilahi yang sama seperti para imam Syiah.
Secara ringkas, meskipun tradisi Syiah memiliki model kepemimpinan yang paling mendekati Paus—bahkan mungkin lebih tinggi dalam hal klaim bimbingan ilahi—saat ini, tidak ada satu pun pemimpin sentral yang dapat menyatukan seluruh umat Muslim, baik bagi tradisi Sunni maupun Syiah.
Mari kita bedah secara mendalam apa manfaat dan risiko dari model kepemimpinan spiritual yang tidak terpusat. Di satu sisi, keunggulan dari memiliki seorang pemimpin sentral yang tunggal sangatlah jelas. Bayangkan sebuah komunitas Muslim global yang bersatu di bawah satu visi dan satu arah yang sama. Konsep ini menjanjikan akhir dari perselisihan internal, penggabungan sumber daya secara efektif, dan koordinasi yang apik dalam berbagai upaya untuk membawa kebaikan bagi masyarakat. Namun, realitasnya, gagasan ini juga menyimpan tantangan yang signifikan.
Kerugian utama terletak pada pertanyaan mendasar: bagaimana kita dapat meyakini bahwa seseorang benar-benar dibimbing secara ilahi? Selama hidup Nabi Muhammad SAW, bimbingan ilahi-Nya terbukti nyata melalui Al-Quran, sebuah mukjizat yang hidup dan abadi. Namun, setelah beliau wafat, klaim bimbingan ilahi dari para pemimpin, bahkan dalam beberapa tradisi, tidak lagi didukung oleh bukti mukjizat yang dapat meyakinkan seluruh umat.
Kondisi ini menimbulkan dilema besar: apakah kita harus mengikuti perintah seorang pemimpin hanya berdasarkan klaim otoritasnya, tanpa bukti meyakinkan bahwa ia benar-benar mendapat bimbingan ilahi? Keraguan semacam ini berpotensi besar memicu kekacauan, perpecahan, dan bahkan anarki. Selain itu, kepemimpinan yang terpusat berisiko mematikan pemikiran kritis dan dinamisme yang lahir dari kebebasan umat untuk memilih pemimpin mereka sendiri.
Meskipun demikian, ada pandangan bahwa sistem yang ditinggalkan dalam tradisi Sunni, meskipun memiliki banyak kekurangan, menawarkan sebuah keunggulan yang tak ternilai: kebebasan berpikir. Pendekatan ini memberi ruang bagi setiap individu dan komunitas untuk berkembang dengan caranya sendiri, berinovasi, dan bahkan bersaing satu sama lain dalam kebaikan. Ini adalah dinamisme yang vital bagi kemajuan dan pertumbuhan komunitas Muslim di era modern.