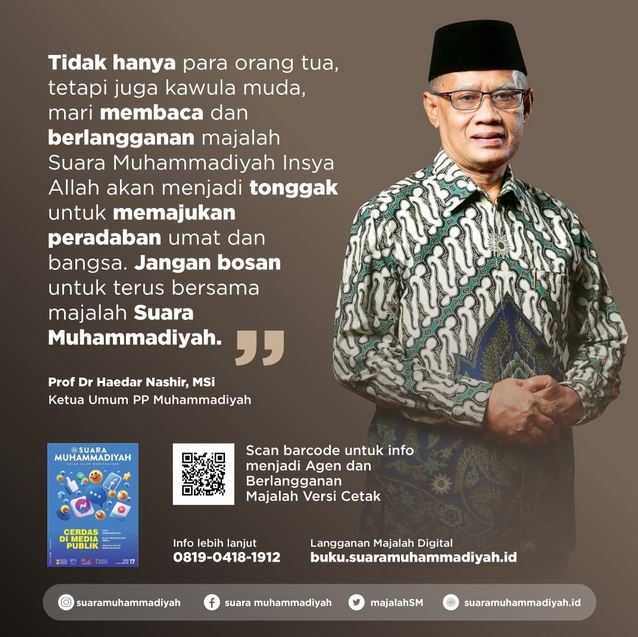Menyoal Garis Kemiskinan Bank Dunia: Membaca Ulang Realitas Kemiskinan Indonesia
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif/Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/Ketua PDM Jakarta Timur / Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia/ Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
Kemiskinan bukan sekadar permasalahan ekonomi, tetapi juga persoalan multidimensional yang mencerminkan ketimpangan, ketidakadilan, dan kegagalan sistemik dalam pembangunan. Selama bertahun-tahun, pengukuran kemiskinan di Indonesia merujuk pada pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menggunakan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimal makanan dan non-makanan. Namun, Bank Dunia juga mengembangkan standar internasional untuk mengukur kemiskinan berdasarkan penghasilan per hari dalam Purchasing Power Parity (PPP).
Perubahan terbaru dari Bank Dunia yang menetapkan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar USD 6,85 per hari telah mengubah wajah statistik kemiskinan Indonesia. Meski angka kemiskinan nasional cenderung menurun, jumlah orang miskin menurut standar Bank Dunia justru melonjak drastis.
Merujuk laporan macro poverty outlook yang dirilis April 2025, Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3 persen atau 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan per September 2024 hanya 8,57 persen atau sekiatr 24,06 juta jiwa.
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa garis kemiskinan menjadi begitu menentukan dalam memahami realitas sosial? Artikel ini akan mengurai secara mendalam kontroversi dan tantangan di balik pengukuran kemiskinan tersebut.
Sebelum kita mengurai lebih lanjut, penting kita memahami dahulu pengertian dan evolusi garis kemiskinan Bank Dunia. Garis kemiskinan adalah ambang batas minimum pendapatan yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Bank Dunia menggunakan beberapa tingkat garis kemiskinan yang dihitung dalam satuan US$ PPP atau purchasing power parity yaitu suatu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Terdapat tiga garis kemiskinan bank dunia yaitu sebesar US$ 2,15 per kapita per hari (kemiskinan ekstrem), untuk negara berpendapatan rendah. Kemudian US$ 3,65 untuk negara berpendapatan menengah bawah. Terakhir adalah US$ 6,85 untuk negara berpendapatan menengah atas, Indonesia dimasukkan oleh Bank Dunia dalam kategori yang terakhir.
Tujuan utama standar ini adalah memberikan alat komparatif global untuk mengevaluasi kemiskinan secara lintas negara. Namun, pendekatan ini juga mengandung kelemahan karena tidak mempertimbangkan konteks lokal seperti struktur harga, kondisi sosial, dan budaya konsumsi suatu negara.
Bank Dunia mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country). Kenaikan ini didasarkan pada Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia yang mencapai USD 4.580 pada tahun 2022, naik 9,8% dari tahun sebelumnya. Ambang batas untuk masuk kategori ini adalah USD 4.466.
Sebelumnya, Indonesia sempat masuk kategori ini pada tahun 2019. Namun akibat pandemi COVID-19, GNI per kapita turun menjadi USD 3.870 pada 2020 dan status Indonesia merosot kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Pemulihan ekonomi pasca pandemi, program PEN, serta kebijakan hilirisasi berhasil mengerek kembali posisi Indonesia.
Perubahan status ini membawa implikasi terhadap pengukuran kemiskinan. Seiring dengan naiknya status pendapatan, garis kemiskinan internasional yang relevan pun naik dari USD 3,65 menjadi USD 6,85. Dampaknya sangat signifikan.
Sedangkan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam menetapkan garis kemiskinan. Komponen utamanya adalah komponen makanan yang dihitung dari kebutuhan kalori minimum (2.100 kkal per kapita per hari). Serta komponen non-makanan yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar perumahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan
Per Maret 2024, garis kemiskinan nasional Indonesia ditetapkan sebesar sekitar Rp 550.458 per kapita per bulan. Sementara jika menggunakan standar USD 6,85 PPP (sekitar Rp 1,7 juta per kapita per bulan), maka jumlah penduduk yang dikategorikan miskin meningkat drastis.
Kesenjangan antara statistik nasional dan internasional memunculkan dilema kebijakan. Pemerintah dapat mengklaim penurunan kemiskinan berdasarkan data BPS, namun komunitas internasional melihat Indonesia masih memiliki populasi miskin yang besar.
Kondisi ini akan memengaruhi penyaluran bantuan internasional, prioritas kebijakan pembangunan, persepsi publik dan legitimasi pemerintah, dan target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Selain itu, kesenjangan ini menyiratkan bahwa banyak rumah tangga di Indonesia tergolong "miskin semu" atau "hampir miskin". Mereka mungkin tidak tergolong miskin menurut BPS, tetapi rentan sekali jatuh ke dalam kemiskinan jika mengalami guncangan seperti inflasi, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam.
Banyak ekonom dan aktivis sosial mengkritik pendekatan garis kemiskinan Bank Dunia karena terlalu simplistik dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lokal. Kritik utamanya antara lain mengabaikan dimensi non-material: seperti akses pendidikan, hak atas tanah, dan partisipasi sosial. Kedua, tidak memperhitungkan keragaman geografis, misalkan biaya hidup di Jakarta berbeda jauh dengan di Papua, tetapi angka garis kemiskinan yang digunakan seragam. Ketiga, angka ini rentan digunakan secara politis. Perubahan garis kemiskinan bisa digunakan untuk membenarkan atau menolak klaim keberhasilan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, pengukuran berbasis pendapatan mengabaikan masalah ketimpangan. Dua orang bisa hidup di atas garis kemiskinan, tetapi yang satu memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, sementara yang lain tidak.
Pemerintah Indonesia perlu bersikap adaptif terhadap realitas baru pasca kenaikan status pendapatan. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, revisi strategi penanggulangan kemiskinan: dari sekadar pendekatan bantuan sosial menuju pembangunan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi.
Kedua, targetkan kelompok "rentan miskin": mereka yang hidup di antara garis BPS dan garis USD 6,85 adalah kelompok terbesar yang berisiko terperosok kembali. Ketiga, perluas cakupan data dengan melakukan integrasikan data kemiskinan moneter, multidimensional, dan spasial untuk analisis yang lebih presisi. Keempat, Fokus pada pembangunan daerah khususnya kawasan timur Indonesia yang memiliki kemiskinan struktural.
Garis kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan cermin dari bagaimana suatu negara menilai dan merespons penderitaan warganya. Kenaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas adalah prestasi, tetapi sekaligus tantangan. Standar hidup masyarakat harus menyesuaikan dengan ekspektasi global.
Perbedaan besar antara angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia harus menjadi alarm bahwa kemiskinan belum benar-benar tertanggulangi. Selama masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, maka kemiskinan tetap menjadi realitas yang menjerat jutaan orang.
Sudah saatnya kita meninggalkan pendekatan sempit yang hanya berfokus pada angka dan mulai merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan manusia yang nyata. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya naik kelas secara statistik, tetapi benar-benar maju dalam hal kesejahteraan rakyatnya.