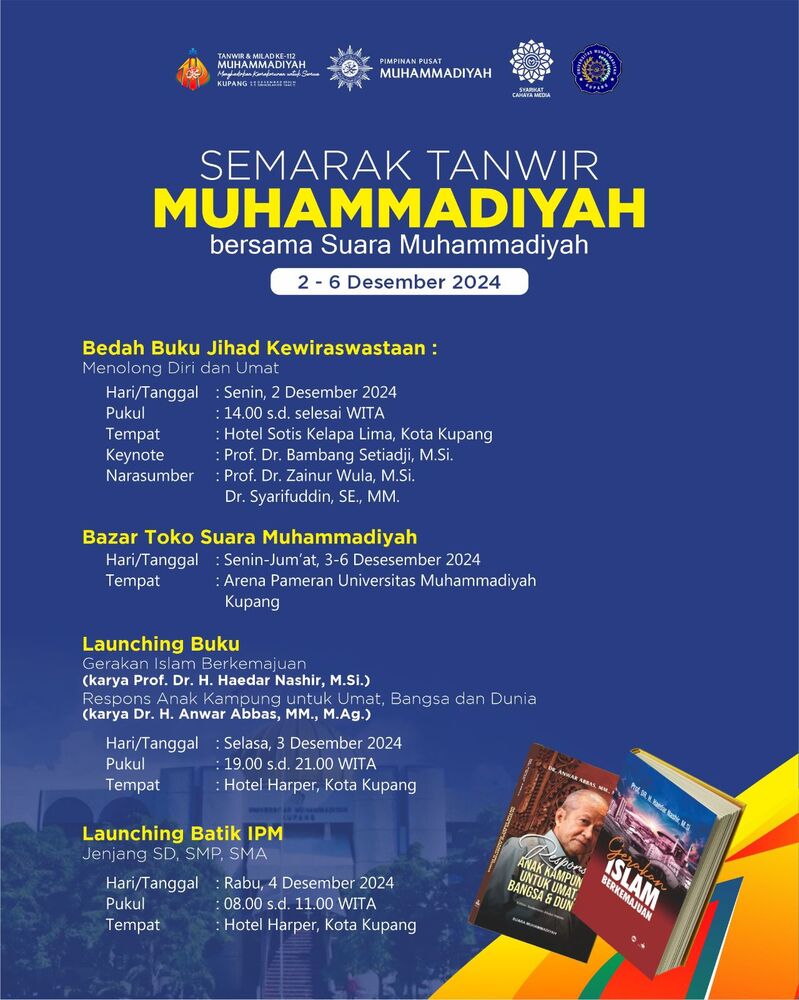Press Release Direktorat Komunikasi Publik UMY
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Kualitas demokrasi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam acara Bedah Riset: Dinamika Narasi Politik dan Preferensi Pemilih yang diselenggarakan oleh Yayasan LKiS pada Kamis (30/10) secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam forum tersebut, Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menilai bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan tengah mengalami kemunduran signifikan, terutama dalam aspek kebebasan sipil.
Merujuk pada temuan riset Yayasan LKiS yang mengambil studi kasus di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, Ridho menyebut hasil penelitian itu memperkuat berbagai laporan lembaga internasional yang telah lebih dahulu mengkritik kondisi demokrasi Indonesia.
“Freedom House melabeli demokrasi Indonesia sebagai partly free atau semi-demokratis. Bahkan sejak 2014 hingga saat ini, kondisi kebebasan sipil kita masih buruk,” ungkap Ridho.
Ia mencontohkan berbagai kasus penindasan terhadap media, seperti Tempo, serta pembatasan terhadap organisasi masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa negara semakin bersikap antikritik, yang justru melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.
Lebih jauh, Ridho juga mengutip laporan tahunan The Economist Intelligence Unit yang menempatkan Indonesia sebagai flawed democracy atau demokrasi cacat. Ia menganalogikan situasi tersebut seperti tubuh yang sedang menderita penyakit kronis: kritik yang seharusnya menjadi “jamu pahit tapi menyehatkan” justru diberangus, sementara praktik kekuasaan yang “manis tapi merusak” seperti monopoli tambang dan perilaku antikritik dibiarkan tumbuh subur.
Temuan riset Yayasan LKiS juga mengungkap bahwa isu demokrasi di masyarakat akar rumput sering kali dianggap sebagai “isu elit”. Dengan mengutip data Kementerian Dalam Negeri, Ridho menyoroti masih tingginya tingkat pendidikan rendah di beberapa daerah, sekitar 23 persen hanya tamat SD dan 23 persen lainnya belum bersekolah, termasuk bayi, yang membuat kebutuhan utama masyarakat bukanlah soal partisipasi politik, melainkan penghidupan yang layak.
“Bagi masyarakat di tingkat bawah, yang penting bukan pencoblosan, tapi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan. Di beberapa daerah bahkan praktik pemilu masih seperti sistem noken, di mana suara masyarakat digerakkan secara kolektif,” jelasnya.
Ridho juga menyoroti ironi antara demokrasi dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Ia membandingkan Indonesia yang memiliki sistem politik “demokratis” tetapi stagnan secara ekonomi, dengan Malaysia yang justru mengalami perbaikan ekonomi meski secara politik sering berganti perdana menteri.
Sebagai penutup, Ridho mengutip analogi Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang dinilainya masih relevan dengan kondisi politik saat ini.
“Di Indonesia, Anda tidak boleh mengkritik pemerintah, apalagi mencaci maki. Tapi, carilah uang sendiri,” tuturnya.
Menurut Ridho, kondisi ini menggambarkan kejenuhan publik terhadap demokrasi elektoral, dimana proses politik berjalan, tetapi substansi kebebasan dan keadilan sosial semakin terpinggirkan. (FU/hanan)