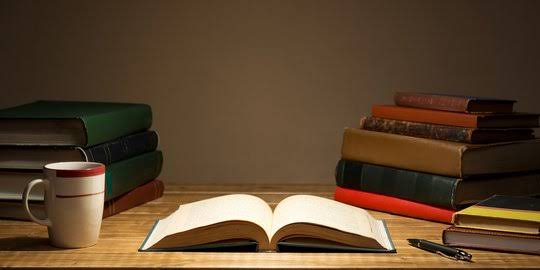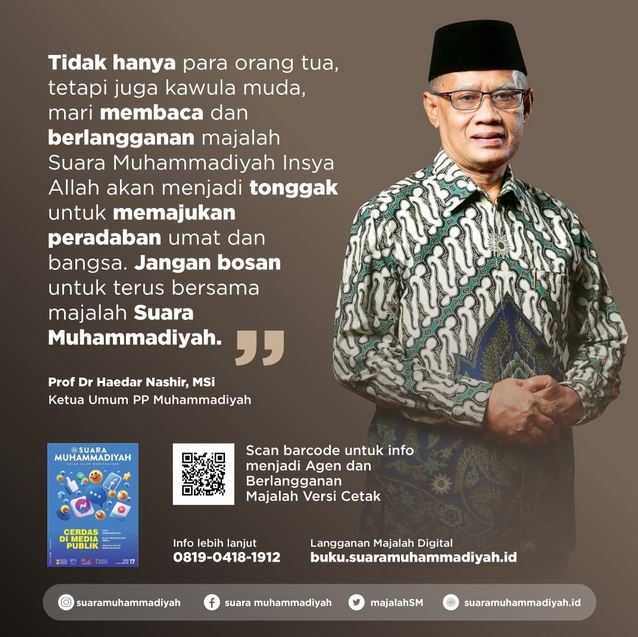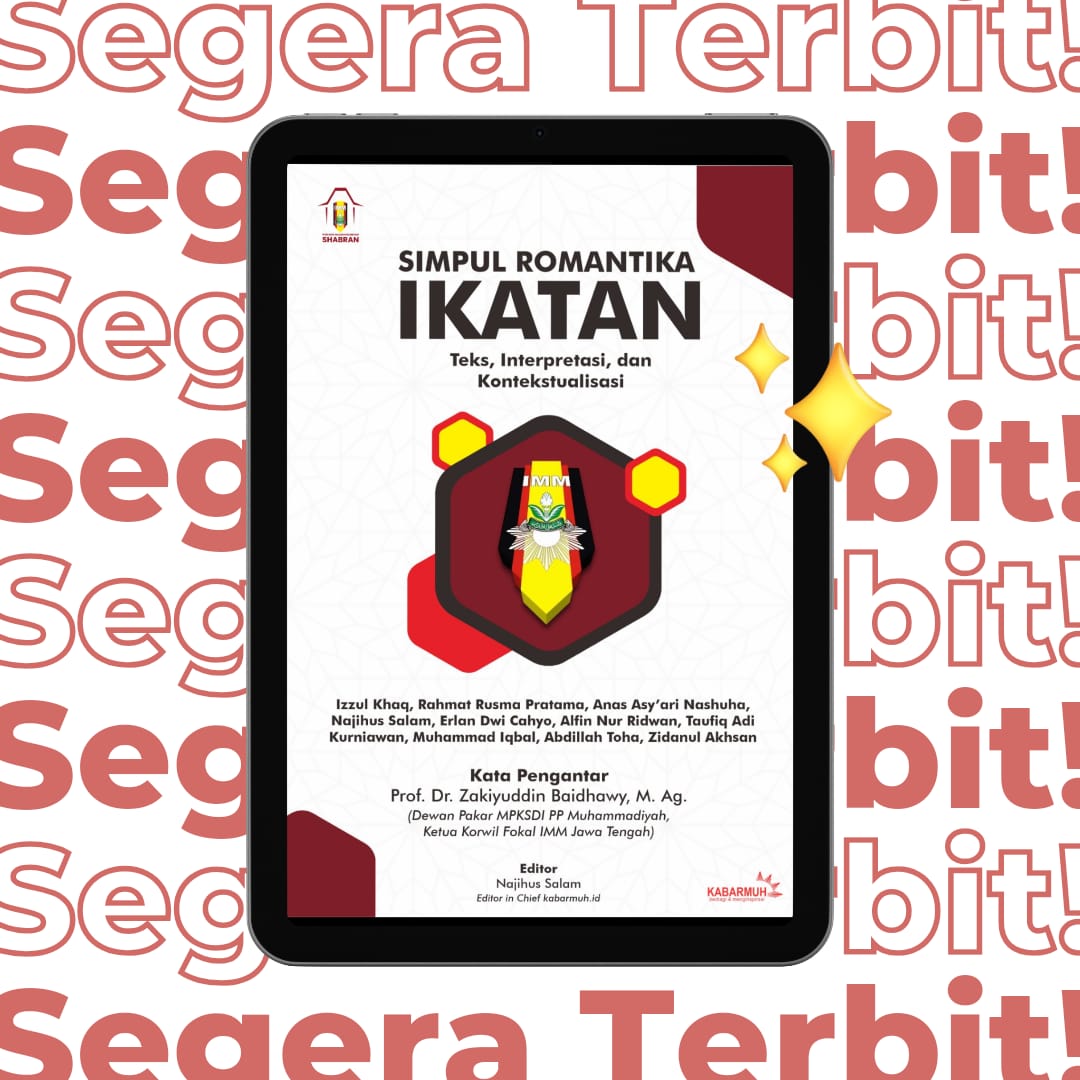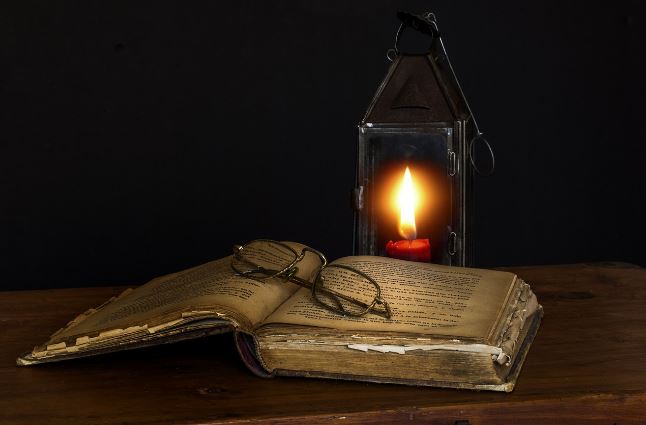Alhamdulillah dan Empati Sosial
Oleh: Hatib Rachmawan, Dosen Prodi Ilmu Hadis FAI Universitas Ahmad Dahlan
Beberapa waktu lalu, sebuah kejadian kecil di grup WhatsApp seleksi sertifikasi dosen membuat saya merenung panjang. Begitu pengumuman hasil keluar, beberapa anggota grup dengan cepat menuliskan ucapan selamat dan “alhamdulillah” kepada rekan-rekan yang lulus. Sekilas tampak wajar, bahkan indah: sebuah ekspresi syukur dan apresiasi terhadap kabar baik. Namun, ada yang terasa mengganjal. Bagaimana perasaan mereka yang tidak lulus ketika membaca rentetan ucapan itu?
Saya pun menuliskan komentar: “Apakah kita harus mengucapkan selamat? Sementara 1 atau beberapa orang sedih membaca ucapan selamat di grup ini.” Seketika percakapan grup terhenti. Hening. Saya bisa membayangkan, sebagian mungkin heran dengan komentar itu, sebagian lain barangkali merenung. Tujuan saya sederhana: menjaga roso—kepekaan terhadap perasaan orang lain—agar komunikasi tidak tanpa sadar melukai hati yang tengah rapuh.
Antara Syukur dan Luka
Fenomena semacam ini sering muncul di ruang publik, baik offline maupun online. Dalam sebuah komunitas, kabar gembira selalu berdampingan dengan kabar duka. Ada yang berhasil, ada pula yang belum beruntung. Ketika kita hanya merayakan yang berhasil tanpa menimbang perasaan yang lain, komunikasi bisa berubah menjadi eksklusif. Ucapan selamat yang niatnya tulus justru bisa terasa seperti garam yang ditaburkan ke atas luka terbuka.
Padahal, dalam tradisi keagamaan maupun budaya, mengucapkan selamat dan syukur adalah tindakan mulia. Akan tetapi, sebagaimana setiap kebajikan, konteks menentukan makna. Di ruang publik yang berisi beragam pengalaman—ada yang sukses, ada yang gagal—ungkapan syukur memerlukan kerangka empati agar tidak menyisakan luka sosial.
Psikolog humanis Carl Rogers (1961) mendefinisikan empati sebagai kemampuan untuk “to sense the client’s world as if it were your own”—merasakan dunia orang lain seakan-akan itu dunia kita sendiri. Dalam komunikasi digital, empati berarti berhati-hati memilih kata, menimbang waktu, dan mempertimbangkan audiens yang heterogen.
Ucapan selamat tentu tidak salah, tetapi lebih baik jika dibingkai secara inklusif. Misalnya: “Selamat untuk yang lulus, semoga menjadi inspirasi. Bagi yang belum, semoga diberi kesempatan lebih baik di masa depan.” Dengan cara ini, kita tidak hanya merayakan keberhasilan, tetapi juga merangkul mereka yang masih berproses. Komunikasi tidak sekadar menyampaikan pesan, melainkan membangun solidaritas.
Latah Sosial di Dunia Digital
Ada sisi lain yang tak kalah menarik: fenomena kelatahan sosial. Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai bandwagon effect atau herd behavior: ketika seseorang melakukan sesuatu (misalnya mengucapkan selamat), anggota lain cenderung menirunya tanpa refleksi kritis. Robert Cialdini (2007) menyebutnya sebagai social proof: manusia terdorong mengikuti mayoritas karena merasa itu jalan aman dan benar.
Di grup WhatsApp, begitu satu ucapan selamat muncul, dalam hitungan menit puluhan ucapan serupa membanjiri layar. Tidak semuanya lahir dari niat personal, sebagian hanya hasil latah digital. Di sinilah persoalan muncul: kelatahan bisa menciptakan suasana semu, di mana kegembiraan mayoritas menutupi kesedihan minoritas.
Latah sosial ini sebenarnya netral. Ia bisa mempercepat solidaritas, bisa pula menyingkirkan empati. Masalahnya bukan pada “alhamdulillah” itu sendiri, melainkan pada hilangnya kesadaran reflektif. Kita sering lupa bertanya: Apakah ucapan saya benar-benar menguatkan, atau sekadar mengikuti arus?
Renungan Kritis
Pengalaman sederhana di grup WA itu memberi saya satu pelajaran penting: komunikasi adalah cermin hati. Kata-kata bisa menjadi penawar, tetapi bisa juga menjadi pisau. “Alhamdulillah” akan tetap indah jika dibarengi empati, bukan sekadar latah menyalin ucapan orang lain.
Barangkali, di era digital ini, tantangan kita bukan lagi bagaimana mengekspresikan diri, tetapi bagaimana mengekspresikan diri dengan sadar. Setiap kalimat yang kita tulis di ruang publik akan dibaca oleh orang-orang dengan latar perasaan yang berbeda. Ada yang sedang bahagia, ada yang sedang kecewa. Menulis dengan empati berarti mengingat bahwa pesan kita tidak hanya bergaung ke ruang hampa, melainkan menembus hati manusia yang nyata.
Pada akhirnya, komunikasi yang sehat bukan soal siapa yang paling cepat mengucapkan selamat, atau siapa yang paling religius menuliskan “alhamdulillah”. Komunikasi yang sehat adalah yang mampu menghadirkan kenyamanan kolektif, memberi ruang bagi kegembiraan sekaligus melindungi mereka yang tengah terluka.
Mari belajar berhenti sejenak sebelum menulis. Mari menimbang kata-kata dengan empati. Sebab di balik setiap “alhamdulillah”, ada tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa syukur kita tidak melukai, tetapi merangkul semua.