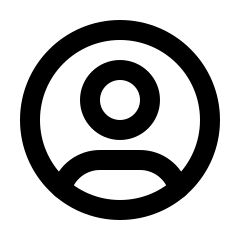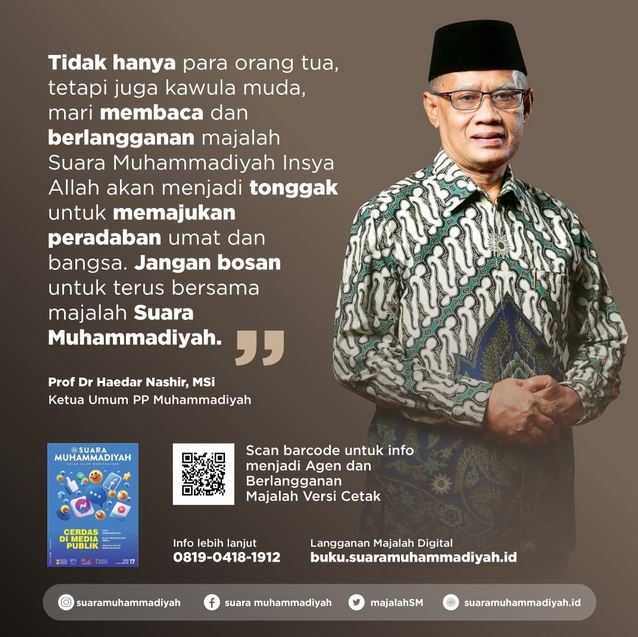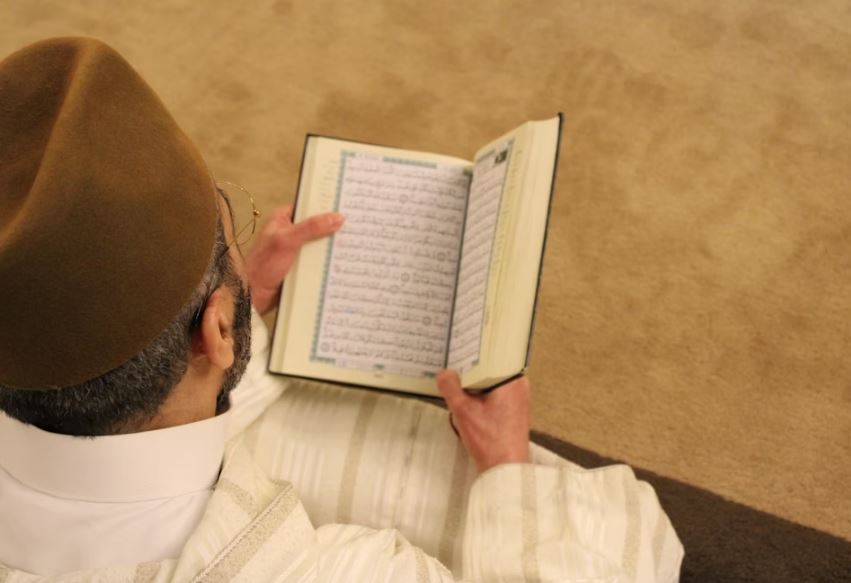Dari Sumpah Menuju Aksi Mencerahkan
Oleh: Yana Fajar FY. Basori
Pemuda Indonesia akan mengalami tantangan hebat bonus demografi 2030. Mereka akan bersaing di bursa pasar kerja. Besarnya populasi pemuda belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi kecuali dilengkapi dengan pendidikan dan keterampilan yang cukup dan dibutuhan pasar kerja.
Berdasarkan data Susenas 2024, diperkirakan terdapat sekitar 64,22 juta jiwa pemuda atau seperlima jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komposisi pemuda laki-laki dan perempuan memiliki selisih yang cukup kecil, hanya sebesar 1,20 persen poin, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,44. Rasio jenis kelamin tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang pemuda perempuan terdapat sekitar 102 orang pemuda laki laki. Lebih dari setengah pemuda tinggal di perkotaan (60,72 persen, sedangkan sisanya sebesar 39,28 persen tinggal di daerah perdesaan.
Pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Pada tahun 2024, hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. Sekitar 28 dari 100 pemuda tercatat sedang bersekolah, dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 16−18 tahun sebesar 74,64 persen, diikuti kelompok umur 19−23 tahun sebesar 29,01 persen, dan kelompok umur 24−30 tahun sebesar 6,33 persen. Secara umum, APS pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan dan terdapat keterkaitan status ekonomi rumah tangga terhadap APS pemuda. Pada tahun 2024, tingkat pendidikan pemuda Indonesia didominasi oleh tamatan SMA/SMK sederajat (40,94 persen). Hanya 11,36 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga PT dan masih terdapat 1 dari 50 pemuda yang tidak pernah bersekolah/tidak tamat SD sederajat.
Kelompok dengan status ekonomi rumah tangga 20 persen teratas memiliki persentase pemuda yang menamatkan pendidikan hingga SMA/SMK sederajat ke atas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Tingkat tingkat pendidikan pemuda juga tercermin melalui rata-rata lama sekolah, yaitu sebesar 11,11 tahun atau setara dengan kelas XI pada jenjang SMA/SMK sederajat. Rata-rata lama sekolah pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan (11,59 tahun berbanding 10,37 tahun). Rata- rata lama sekolah pemuda penyandang disabilitas masih tertinggal jauh dibandingkan pemuda bukan penyandang disabilitas. Secara rata-rata pemuda penyandang disabilitas dapat menamatkan pendidikan hanya sampai kelas VI SD sederajat, sementara pemuda bukan penyandang disabilitas dapat menamatkan sampai kelas XI pada jenjang SMA/SMK sederajat.
Kelompok usia pemuda menempatkan pemuda pada kelompok usia sekolah dan kerja. Data ketenagakerjaan melalui Sakernas Agustus 2024, menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja (56,98 persen), sementara 7,95 persen menganggur. Indikator NEET (Not in Employment Education, and Training) menunjukkan 23,78 persen pemuda usia 16–30 tahun tidak bekerja, tidak bersekolah, atau tidak mengikuti pelatihan. Persentase NEET perempuan (33,10 persen) dua kali lebih tinggi dibanding laki-laki (14,98 persen). Kelompok umur 19–24 tahun memiliki persentase NEET tertinggi (26,37 persen) dibandingkan kelompok umur lainnya. Selain NEET, ada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu indikator yang mengukur besarnya angkatan kerja yang menjadi pengangguran pemuda. Pada 2024, TPT pemuda adalah 12 persen, lebih tinggi dari TPT nasional. TPT pemuda tertinggi terjadi pada tamatan SMA/SMK sederajat (14,39 persen), diikuti tamatan perguruan tinggi (12,01 persen), dan tamatan SMP (8,89 persen). Angkatan kerja pemuda, yaitu penduduk berusia 16–30 tahun, berperan penting dalam perekonomian. Semakin besar angkatan kerja maka diharapkan akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda pada tahun 2024 adalah 64,93 persen. Terdepat kesenjangan gender yang signifikan terkait TPAK, dimana TPAK pemuda laki-laki mencapai 76,43 persen, sementara perempuan 52,77 persen. Pemuda bekerja didominasi oleh tamatan SMA/SMK sederajat (53,88 persen), dengan perbedaan pola pendidikan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, 57,95 persen pemuda bekerja adalah tamatan SMA/SMK sederajat, sedangkan di perdesaan, 41,75 persen adalah tamatan SMP ke bawah. Pemuda perempuan yang bekerja cenderung memiliki pendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki. Lebih dari separuh pemuda bekerja di sektor jasa (56,55 persen), dengan sektor pertanian masih dominan di perdesaan (36,15 persen). Sebagian besar pemuda bekerja di sektor formal (57,20 persen), dengan perbedaan antara perkotaan (67,80 persen) dan perdesaan (42,58 persen).
Tidak sekedar bekerja, indikator pekerjaan layak yaitu Precarious Employment Rate (PER) dan Low Pay Rate (LPR) perlu mendapat perhatian. PER mengukur stabilitas dan jaminan pekerjaan, sementara LPR mengukur pendapatan yang setara dan pekerjaan produktif. Pada tahun 2024, sebanyak 54,36 persen pemuda bekerja termasuk dalam kategori pekerja tidak tetap (precarious employment), dengan angka lebih tinggi pada pemuda laki-laki (57,79 persen) dan pemuda yang tinggal di daerah perkotaan (60,50 persen). LPR menunjukkan bahwa 28,98 persen pemuda bekerja dengan upah rendah, terutama dialami oleh pemuda perempuan (37,53 persen) dan pemuda di perdesaan (39,92 persen). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jam kerja maksimal 40 jam per minggu, dengan dua sistem yakni 7 jam per hari untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja. Data Sakernas 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda, bekerja dengan jam kerja lebih dari 40 jam per minggu. Sementara itu, sekitar 24,79 persen pemuda bekerja dengan jam kerja berlebih (Employment in Excessive Working Time/EEWT). Jam kerja berlebih didefinisikan sebagai lebih dari 48 jam yaitu jam kerja lebih dari 48 jam per minggu (BPS 2023:P 9).
Di sisi lain, sebanyak 31,14 persen pemuda bekerja kurang dari 35 jam perminggu, capaian tersebut lebih banyak terjadi di perdesaan dan pada pemuda perempuan. Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa dari 100 pemuda bekerja, 18 di antaranya adalah pemuda pengusaha, dengan mayoritas berstatus/kedudukan sebagai berusaha sendiri (12,77 persen). Pemuda pengusaha paling banyak ditemukan di sektor jasa (75,43 persen), sementara yang berstatus berusaha dengan dibantu pekerja tidak dibayar terbanyak di sektor pertanian (38,19 persen). Indikator lainnya yaitu pemuda berusaha dengan status white collar. Indikator ini didefinisikan sebagai persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha (baik itu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap), dengan jenis pekerjaan white collar (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) terhadap seluruh pemuda.
Tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yaitu alat ukur pembangunan pemuda yang mengadopsi Youth Development Index (YDI) dengan penyesuaian dimensi dan indikator, menjelaskan kondisi pemuda Indonesia dalam lima (5) domain, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi, menunjukkan domain partisipasi dan kepemimpinan terus stagnan dalam empat tahun terakhir. Diperlukan cara-cara yang tepat untuk meningkatkan keterampilan maupun pembekalan ulang sehingga lebih produktif dan kompetitif mendukung bonus demografi 2030. Peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda adalah memontum memperbaiki IPP terutama domain partisipasi dan kepemimpinan dengan meningkatkan pendidikan, dan keterampilan (upskilling) maupun pembekalan ulang (reskilling).
Dari Sumpah menuju Aksi
Data dan fakta pemuda ketika Sumpah Pemuda dibacakan, mungkin tidak lebih bagus dari gambaran pemuda tahun 2024. Yang pasti adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi penanda unggul pemuda yang berhasil dengan usaha intelektual mereka mensitesiskan keragaman anasir keindonesiaan, dua dekade setelah deklarasi Budi Utomo Pernyataan ‘Sumpah Pemuda’ tersebut mempertautkan segala keragaman ke dalam kesatuan tanah air dan bangsa, dengan menjungjung bahasa persatuan.
Melalui ‘Sumpah Pemuda’, seperti diungkapan Yudi Latif (2015), kaum muda berusaha menerobos batas-batas sentimen etno-religius (etno-nationalism) dengan menawarkan fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan (citizenship) yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa dan bahasa persatuan (civic nationalism). Penduduk Indonesia menjadi ‘pribumi’, bahkan bagi mereka mereka yang berlatar imigran. Kita tidak dituntut apapun dengan keberhasilan pemuda 1928, tetapi akan dituntut untuk terlibat memproses pemuda hari ini menjadi pemimpin di masa depan ditengah jebakan demografi dan menguatnya dominasi elit dalam politik formal dan informal. Opini Tempo (20-26 Oktober 2025) menyebutnya, ‘konsolidasi otoritarian’. Sebagaimana keterlibatan pelajar, mahasiswa, pemuda dalam asal mula pergerakan anti-kolonial Indonesia, maupun masyarakat luas, tidak dapat disebutkan atau diperkirakan tanggalnya secara tepat, namun demikian reaksi negatif yang sering disematkan kepada kaum tani dapat menjadi penanda perlawanan yang sering kuat, spontan tanpa dorongan pemimpin nasionalis.
Mereka mewakili perlawanan politik melalui protes yang melibatkan banyak keluarga petani, yang berusaha mengarahkan kekuatan tersebut ke dalam hubungan yang jelas lebih nasionalistik melawan pemerintah Hindia Belanda. Misalnya konfrontasi di sabuk perkebunan Sumatra tahun 1870 (Ann Laura Stoler, 2005), pemberontakan petani Banten tahun 1888 (Kartodirdjo, 1984), protes kaum tani yang disebut dengan gerakan Saminis yang telah dimulai sejak 1890 di Blora (Kahin, 2024). Penculikan pemimpin nasional menjelang deklarasi kemerdekaan `17 Agustus 1945, ‘revolusi dalam revolusi’ seperti dikemukakan Anton Lucas (2019) yang menjelaskan tentang peristiwa penting di ‘Tiga Daerah’ (Brebes, Pemalang, Tegal) dengan ‘Tiga Peristiwa’, yakni kekosongan kekuasaan, perebutan kekuasaan dan stabilisasi kekuasaan melalui proses marjinalisasi kelompok radikal. Selanjutnya aksi protes tersebut dapat terbaca dari peristiwa menjelang pergantian rezim Sukarno, Suharto hingga protes pada Agustus 2025 yang lalu yang seluruhnya menegaskan aksi protes sebagai tradisi dari panggung heroik pemuda. Dalam bukunya yang pertama ditulis, Edward Aspinal (2005), membuktikan bagaimana rakyat biasa dapat membawa perubahan politik di bawah rezim yang represif melalui upaya kelompok oposisi, LSM, aktivis mahasiswa, dan pekerja partai politik. Dalam kasus Aspinal, menentang rezim otoriter Soeharto dan akhirnya memaksanya mundur pada tahun 1998.
Bagian dari aksi heroik adalah mendorong pemuda terlibat dalam berbagai model pendidikan politik kritis, plural dan inklusif. Pendidikan politik kritis berfokus pada peningkatan kapabilitas yang menjadi prasyarat yang tidak boleh tidak dilakukan. Unsur plural hendak menyatakan bahwa dalam demokrasi ada dua unsur konstitutif yang saling berkaitan yaitu pluralisme kepentingan dan nilai yang dimiliki bersama dalam kelompok, dan keterbukaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lainnya. Unsur inklusif hendak mengatasi strategi politik eksklusif kaum populis dengan menonjolkan politik inklusi yang terbuka bagi semua bagian dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek imparsialitas, refleksivitas dan proksimitas (Pius Pandor CP, 2024).Yang paling pokok, tentu saja 97 tahun Sumpah Pemuda bukan hanya bahan pidato dengan gempita nasionalistik tetapi terjebak dalam perangkap bonus demografi.