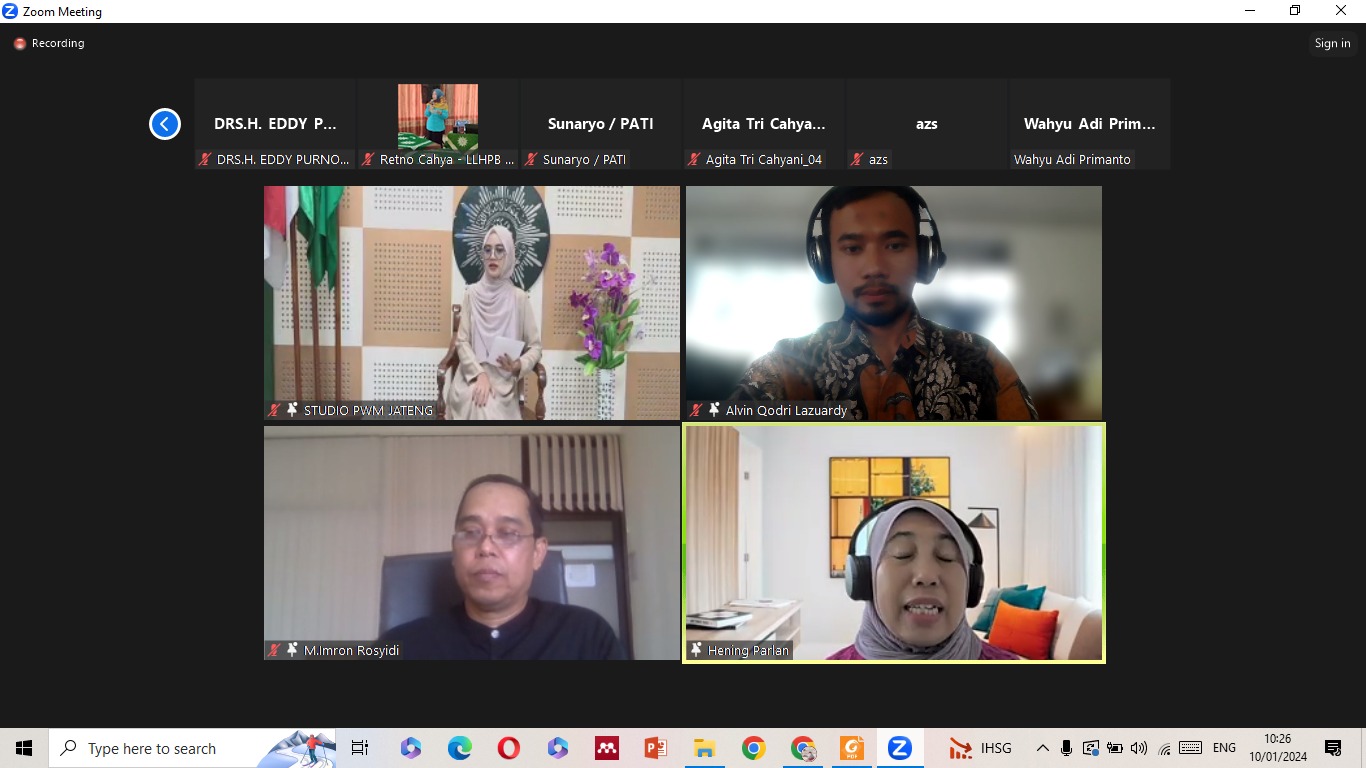MALANG, Suara Muhammadiyah - Berbekal kemudahan dalam satu genggaman, sistem pembayaran nontunai QRIS kini menjadi primadona di kalangan mahasiswa Gen Z. Namun, di balik kepraktisan tersebut, tersimpan risiko finansial berupa ilusi digital yang sering kali tidak kasat mata bagi para penggunanya. Dosen Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ainur Rifqi Almahdani Rahmat, M.M., menyoroti fenomena ini sebagai pemicu utama terkikisnya kesadaran finansial anak muda.
Rifqi sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa secara psikologis, bertransaksi dengan QRIS terasa sangat berbeda dibandingkan dengan mengeluarkan lembaran uang fisik dari dompet. Saat menggunakan uang tunai, seseorang akan merasakan sensasi "kehilangan" yang nyata karena fisik uang benar-benar berpindah tangan dan terlihat berkurang. Sebaliknya, pembayaran digital membuat hambatan psikologis untuk belanja menjadi sangat rendah karena prosesnya yang terlalu instan. Kondisi inilah yang memicu munculnya latte factor, yaitu pengeluaran kecil rutin seperti kopi atau jajanan yang sering dianggap remeh namun berdampak signifikan pada tabungan di akhir bulan.
“Secara psikologis, ketika kita mengeluarkan uang fisik, ada sensasi kehilangan yang benar-benar terasa. Namun saat menggunakan QRIS, perasaan itu cenderung memudar karena prosesnya sangat singkat, cukup klik, scan, lalu transaksi selesai,” ungkapnya pada tim humas UMM pada 19 Januari lalu.
Sistem QRIS sejatinya memiliki keuntungan besar, seperti kemudahan transaksi tanpa perlu repot membawa uang kembalian dan pencatatan otomatis di aplikasi. Namun, kekurangannya terletak pada kontrol diri yang sering kali melemah akibat iming-iming promo cashback. Ia menjelaskan bahwa promo tersebut merupakan strategi bisnis untuk membentuk kebiasaan belanja yang berkelanjutan (repeat order). Konsumen yang semula tidak butuh, akhirnya terdorong membeli hanya karena merasa mendapatkan diskon, padahal secara jangka panjang justru perusahaanlah yang paling diuntungkan.
“Dalam jangka panjang, perilaku konsumtif naik karena terbentuk kebiasaan baru, yang semula bukan kebutuhan menjadi keinginan karena adanya promo, sehingga akhirnya terjadi repeat order secara terus-menerus,” jelasnya.
Bahaya jangka panjang dari ilusi saldo digital ini adalah mentalitas keuangan yang menjadi tidak disiplin karena nilai uang terasa lebih abstrak. Tanpa adanya evaluasi berkala, terkhusus Gen Z berisiko mengalami defisit anggaran karena merasa saldonya masih mencukupi padahal pengeluaran harian sudah melampaui batas yang ditentukan. Sebagai langkah antisipasi hal itu, Rifqi menyarankan penggunaan satu aplikasi khusus untuk pembayaran harian. Supaya mempermudah rekapitulasi dan evaluasi pengeluaran bulanan.
“Gunakan satu aplikasi khusus untuk transaksi QRIS, lalu biasakan mengecek rekap pengeluaran bulanan agar tujuan keuangan jangka panjang tetap terjaga dan tabungan tidak habis oleh pengeluaran kecil yang sering tidak terasa,” pungkasnya.
Strategi ini diharapkan mampu membantu mahasiswa tetap menikmati kemudahan teknologi tanpa harus kehilangan kendali atas kondisi finansial mereka. Dengan perencanaan yang matang, Gen Z tetap bisa menjalani gaya hidup cashless yang bijak sekaligus aman dari jebakan konsumerisme berlebih. (diko)