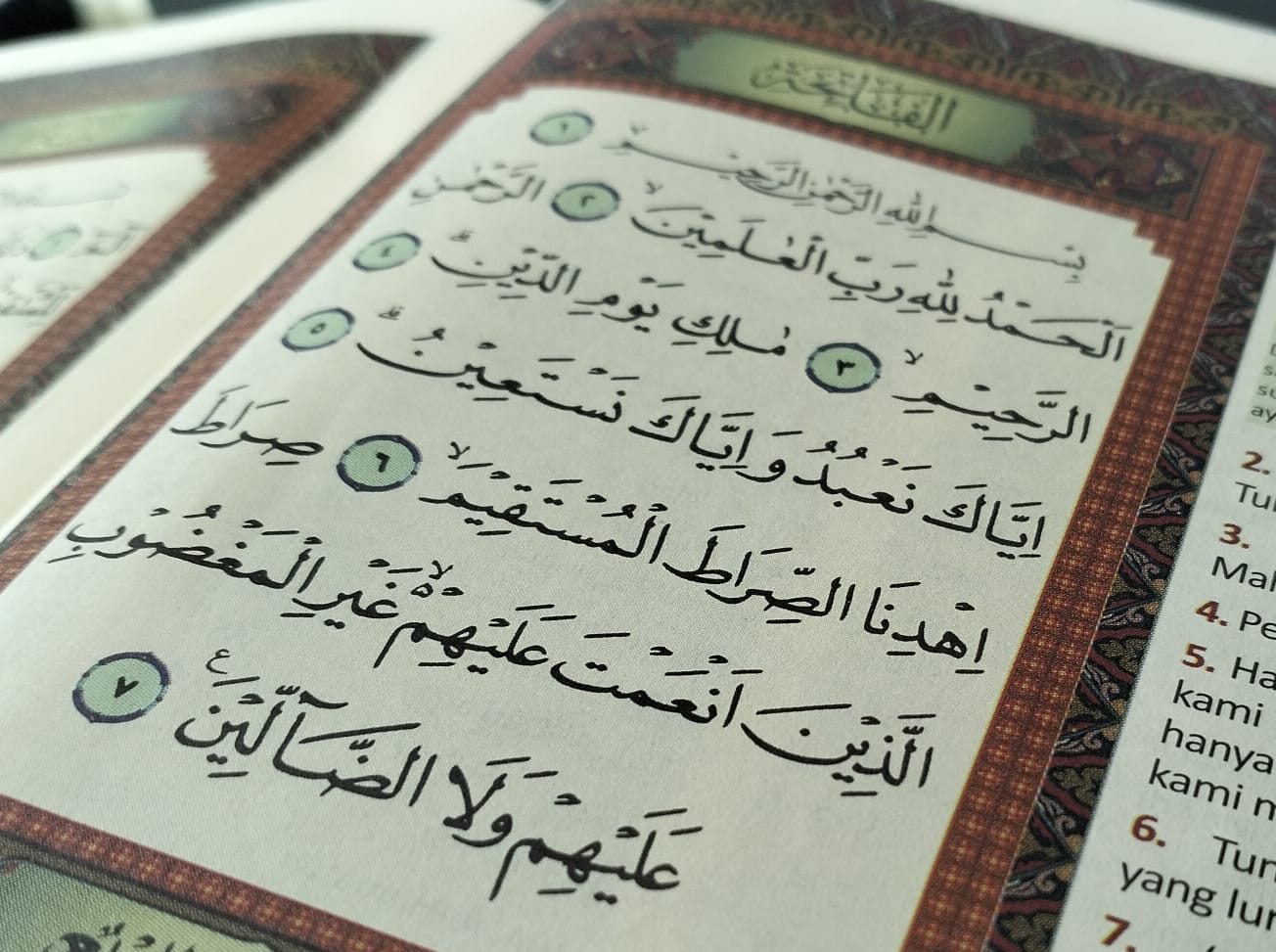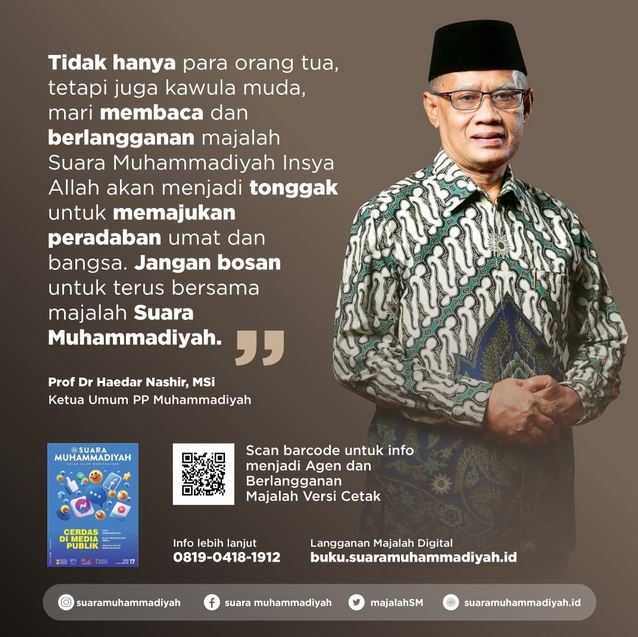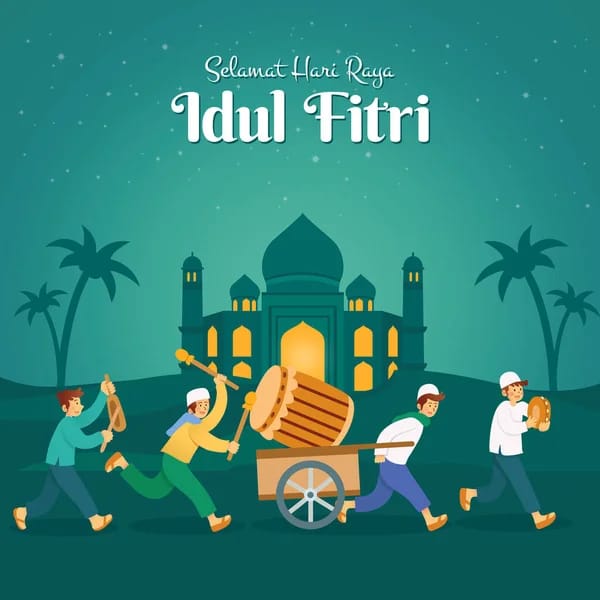Fardhu Kifayah di Era Jempol: Saat Empati Berhenti di Layar
Oleh: Ratna Arunika
Di tengah reruntuhan puing-puing bencana alam yang masih berasap, kita sering menjumpai orang-orang datang berbondong-bondong bukan untuk membawa obat dan selimut, melainkan ponsel dan tripodnya. Mereka merekam tangis, debu dan luka, mengabadikan derita menjadi konten cerita. Seolah empati kini bisa diukur dengan jumlah like dan comment dari netizen di dunia maya. Sementara para relawan berjuang menembus kerumunan, mengevakuasi korban di antara tatapan pasif para “penonton kemanusiaan”. Area bencana bagi sebagian orang seolah menjadi tempat wisata.
Pemandangan serupa tampak di jalan-jalan kota: ketika tubuh tergeletak di aspal, darah bercampur dengan sinar lampu kendaraan, dan detik-detik hidup seseorang di ujung bahaya, kamera ponsel justru lebih cepat terangkat dari pada memberikan pertolongan pertama . Yang dilakukannya bukan menanyakan identitas korban atau memanggil ambulans, melainkan menekan tombol rekam agar bisa menjadi yang tercepat mengabarkan di dunia maya. Di era digital, tragedi sering kali lebih dari sekedar konten, bukan panggilan nurani.
Kita hidup di “era jempol”, zaman dimana satu sentuhan di layar dapat menyalakan kebersamaan, namun juga dengan mudah memadamkan kepedulian. Empati kini sering berhenti pada tombol like, share, atau tagar solidaritas , tanpa benar-benar berubah menjadi tindakan nyata. Di tengah derasnya arus dunia maya, rasa peduli menjelma jadi performa sosial semata, tampak aktif, tapi tanpa aksi.
Fenomena ini diam-diam berkelindan dengan konsep fardhu kifayah, kewajiban kolektif dalam Islam yang gugur bila sebagian umat telah melakukannya. Di ruang digital, makna luhur itu sering direduksi menjadi pembenaran pasif: “sudah ada yang bantu” “sudah banyak yang bersuara,” atau “aku sudah ikut menyebarkan kontennya”. Ayoub (1999), menjelaskan bahwa “Fardh kifayah embodies the moral dynamics of communal responsibility, yet may also justify passivity when responsibility is believed to have been fulfilled by others.” Dalam konteks virtual, tanggung jawab sosial pun sering berhenti di ilusi partisipasi.
Fardhu kifayah dalam konteks ini mengandung paradoks moral: di satu sisi menumbuhkan solidaritas sosial, namun di sisi lain dapat menjadi pembenaran atas sikap diam ketika seseorang merasa tanggung jawabnya diambil alih oleh orang lain. Fenomena ini semakin diperkuat oleh teori psikologi seperti bystander effect, dimana semakin banyak orang yang menyaksikan, semakin kecil kemungkinan seseorang bertindak.
Fenomena Yang Membunuh Empati
Di dunia yang semakin terhubung oleh jaringan, justru nurani kita semakin terputus. Linimasa setiap hari dipenuhi tragedi, bencana, dan ketidakadilan. Paparan berlebih terhadap emosi digital menciptakan cognitive overload, membuat seseorang sulit membedakan mana yang layak ditanggapi dan mana yang harus diabaikan. Jempol hanya berhenti pada tanda like atau emoji sedih. Seolah empati digital cukup menggugurkan kewajiban sosial. Hal ini melahirkan kondisi “kebas batin digital” atau emotional numbing.
Information overload juga menimbulkan kelelahan empatik (compassion fatigue), dimana terlalu sering melihat penderitaan daring membuat otak membangun mekanisme perlindungan, menumpulkan reaksi emosional. Inilah akar digital bystander effect.
Menurut Walther, media digital menghilangkan sinyal nonverbal penting untuk memahami emosi dan urgensi, sehingga mengurangi respon empatik. Ketika keteraturan moral melemah dan individu kehilangan makna bersama, muncullah anomi sosial. Media sosial menjanjikan kedekatan, tapi kerap melahirkan ilusi kebersamaan, menjadikan komunikasi kehilangan ruh kemanusiaan.
Esperimen klasik The Good Samaritan oleh Darley dan Batson menunjukan bahwa empati tidak selalu berujung pada tindakan, terutama ketika seseorang dikejar waktu. Di masyarakat modern yang serba cepat, kita tahu dan peduli, tetapi “tidak sempat” bertindak. Urgensi sosial kini bukan lagi kurangnya empati, melainkan hilangnya ruang batin untuk menindaklanjutinya.
Fenomena lain yang memperkuat kebisuan moral di dunia digital adalah spiral of silence (Elisabeth Noelle-Neuman), di mana individu memilih diam saat pandangannya tidak sejalan dengan opini mayoritas. Ketakutan akan juhatan atau social backlash membuat banyak orang lebih nyaman menjadi penonton moral ketimbang pelaku sosial.
Namun diam itu sering menipu. Banyak orang yang sebenarnya tidak setuju dengan pendapat mayoritas, tetapi mengira semua orang berpikiran sama. Inilah pluralistic ignorance, salah paham secara kolektif yang menimbulkan budaya pasif. Ketika spiral of silence dan pluralisme ignorance bersatu, lahirlah ruang sosial yang ramai tapi hampa makna. Banyak yang berbicara, tapi sedikit berpikir.
Di dunia maya, kita semua menjadi penonton. Kita menyimak, menilai, memberi reaksi. Namun, siapa yang benar-benar bertindak? Empati yang dangkal dari interaksi digital membuat hubungan antar manusia kehilangan kedalaman. Kita mudah tersentuh, tetapi sulit terhubung. Secara psikologis, hal ini memicu kelelahan emosional, kecemasan, depresi, dan rasa terisolasi karena koneksi yang dibangun hanya sebatas layar.
Secara sosial, solidaritas komunitas perlahan menurun, kepedulian menjadi kesopanan digital belaka. Fenomena seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial tumbuh dari akar yang sama, hilangnya ruang dialog dan keberanian bersuara.
Perspektif Islam dan Jalan Keluar
Dalam budaya Muslim, gejala ini berakar pada salah tafsir terhadap nilai fardhu kifayah. Kewajiban sosial yang seharusnya menumbuhkan tanggung jawab kolektif, justru dijadikan alasan untuk diam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kepedulian yang berhenti pada niat. Empati yang berhenti di layar, bila dibiarkan akan menumpulkan nurani dan menjauhkan manusia dari hakikat kemanusiaanya.
Islam mengajarkan tindakan nyata. Qs. Al-Ma’idah (5):2 menegaskan:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."
Rasulullah SWA juga bersabda:
"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya dalam kesulitan, dan tidak menghinanya." (HR. Bukhari).
Pesan ini menekankan empati aktif, bukan diam di layar. Islam memandang kepedulian sebagai panggilan untuk bertindak dalam amar ma’ruf nahi munkar. Mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, termasuk di dunia maya.
Fenomen digital yang membunuh empati dapat dilawan dengan semangat fardhu kifayah sejati, tanggung jawab bersama untuk menolong, berbagi, dan peduli secara nyata. Dunia maya seharusnya menjadi jembatan nurani, bukan tembok yang memisahkan empati.
Islam tidak hanya menyeru kita untuk peduli, tetapi juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):148:
وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
“Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan (fastabiqul khoirot). Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua; sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
Ayat ini menjadi panggilan agar empati tidak berhenti di layar, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata. Kebaikan tidak menunggu viral, dan kepedulian tidak menunggu banyak yang memulai. Dalam setiap kesempatan, bahkan di ruang digital, kita diajak untuk menjadi yang tercepat dalam menolong, menyebarkan kebaikan, dan menyalakan cahaya kemanusiaan.
Mari ubah like menjadi langkah, share menjadi solidaritas, dan tagar menjadi doa yang menggerakan kebaikan. Sebab dihadapan Allah, yang dinilai bukan seberapa sering kita menyentuh layar, tetapi seberapa sungguh hati kita tergerak untuk berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khoirot, demi menolong sesama dan menegakkan nilai kemanusiaan. (hanan)