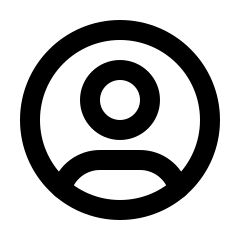Intelektual Tanpa Nurani
Oleh: Suko Wahyudi, PRM Timuran Yogyakarta
Di tengah gegap gempita zaman yang mengagungkan data, gelar, dan logika, kita menyaksikan kemerosotan yang lebih halus tetapi mematikan: lahirnya intelektual tanpa nurani. Mereka yang fasih mengurai teori, namun kehilangan rasa tanggung jawab moral terhadap realitas. Mereka yang mengaku cendekia, tetapi hanya mengulang kata-kata indah tanpa keberanian untuk membela kebenaran.
Ilmu, yang semestinya menjadi cahaya penuntun, kini kerap menjadi alat pembenaran bagi kekuasaan. Kata “ilmiah” menjadi jubah kehormatan untuk menutupi kepentingan, sementara rasionalitas dijadikan tameng bagi kelicikan. Akibatnya, lahirlah generasi terdidik yang cerdas secara akademik, tetapi tumpul dalam rasa keadilan.
Dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan:
“Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tetapi mereka lalai terhadap kehidupan akhirat.” (QS. Ar-Rum [30]: 7)
Ayat ini bukan sekadar teguran spiritual, melainkan peringatan epistemologis: bahwa pengetahuan duniawi yang tak dibingkai dengan kesadaran Ilahi akan kehilangan maknanya. Ilmu menjadi sekadar alat, bukan jalan menuju kebijaksanaan.
Ketika Ilmu Kehilangan Jiwa
Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luhur pula moralnya. Padahal, sejarah membuktikan: tidak sedikit pelaku kejahatan sosial justru datang dari ruang-ruang berpendidikan. Ada intelektual yang menulis tentang demokrasi, tetapi diam ketika rakyat ditindas. Ada sarjana yang mengajarkan etika publik, tetapi turut menikmati praktik korupsi.
Krisis ini menunjukkan bahwa ilmu yang tercerabut dari nurani hanyalah pengetahuan tanpa jiwa. Ia tidak melahirkan kebijaksanaan, melainkan kecerdasan yang kering. Dalam tradisi Islam, ilmu selalu dipadukan dengan hikmah, kebijaksanaan yang menghubungkan akal dengan hati. Seorang alim sejati bukan hanya tahu, tetapi juga takut kepada Allah; bukan hanya berpikir benar, tetapi hidup dalam kebenaran.
Sayangnya, dunia akademik modern sering menyingkirkan dimensi spiritual itu. Keberhasilan diukur dari jumlah publikasi, bukan kedalaman makna. Penghargaan diberikan pada yang produktif, bukan yang jujur. Maka tidak heran jika banyak intelektual yang kehilangan arah: cemerlang di podium, tetapi gelap di ruang batin.
Padahal, tanggung jawab seorang cendekia bukan sekadar menafsirkan dunia, melainkan memperbaikinya. Ilmu harus menjadi cahaya yang menuntun masyarakat menuju kebaikan, bukan sekadar alat untuk menaikkan status sosial. Di sinilah pentingnya nurani — sebagai penuntun moral dalam perjalanan akal. Tanpa nurani, kecerdasan hanyalah topeng. Tanpa keberanian moral, pengetahuan hanyalah hiasan kosong di ruang kuliah.
Kini, bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar orang pintar. Ia membutuhkan orang bijak, mereka yang berani berkata benar ketika banyak yang memilih diam; mereka yang tetap jujur meski kejujuran tak menguntungkan. Sebab intelektual sejati bukan yang pandai berdebat, tetapi yang sanggup menjaga integritasnya di tengah badai kepalsuan.
Maka, tugas kaum terdidik hari ini adalah mengembalikan ilmu kepada fungsinya yang suci: membimbing manusia menuju kebenaran dan kemaslahatan. Sebab ilmu tanpa nurani bukanlah cahaya, melainkan kabut yang menyesatkan.
Akhirnya, ukuran sejati kecendekiaan bukan pada seberapa banyak seseorang tahu, melainkan pada seberapa dalam ia memuliakan kebenaran. Intelektual tanpa nurani mungkin disanjung dunia, tetapi dalam pandangan Tuhan, mereka hanyalah bayang-bayang kosong dari akal yang kehilangan cahaya.(hanan)