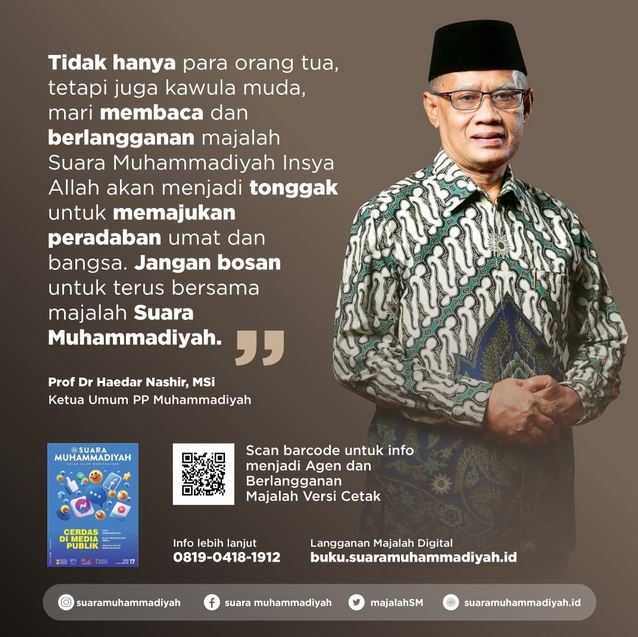Menelaah Relevansi Fiqih Sufistik Al-Ghazali bagi Gerakan Pelajar Muhammadiyah
Oleh: Hakim Muttaqie Azka, mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Pemikiran Imam Al-Ghazali seringkali ditempatkan dalam posisi unik dalam sejarah intelektual Islam karena beliau mampu menyatukan disiplin yang kerap dipertentangkan dalam ranah fiqih, filsafat, dan tasawuf. Dalam kerangka fiqih sufistiknya, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Beliau menegaskan tiga pendekatan penting, yang pertama yakni al-aqliyatu la-syari‘ah yang berpegang teguh pada Al-Qur’an, hadis, dan ijma‘ ulama, dan yang kedua yakni al-aqliyatu al-falsafiyah yang mengapresiasi logika dan nalar filosofis, serta yang ketiganya adalah al-aqliyatu as-shufiyah yang menekankan dimensi pembersihan hati melalui dzikir, mujahadah, dan penyucian jiwa. Hal ini yang melahirkan sebuah paradigma keberagamaan yang seimbang bagi seorang Muslim yang tidak cukup hanya taat pada aturan hukum formal, tetapi juga perlu memiliki kejernihan akal dan keluhuran spiritual. Inilah mengapa pemikiran Al-Ghazali kerap dianggap sebagai jembatan antara dunia syariat dan dunia batiniah. Pemahaman yang demikian membuka ruang bagi generasi Muslim, termasuk para pelajar, untuk menjalani keberagamaan yang komprehensif, bukan parsial.
Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa akal memiliki posisi penting, tetapi tidak boleh melampaui wahyu. Bagi dirinya akal merupakan instrumen untuk memahami realitas, sementara wahyu adalah cahaya kebenaran yang mutlak. Tanpa bimbingan wahyu, akal akan mudah jatuh pada spekulasi, maka beliau mengkritik keras filsafat metafisika yang terlalu mengagungkan rasio hingga menafikan peran Tuhan dalam penciptaan alam atau dalam mengetahui hal-hal partikular.
Bagi Imam Al-Ghazali, posisi akal dan wahyu harus bersifat saling melengkapi, bahwa kebenaran tidak lahir dari dominasi salah satunya, melainkancdari harmoni keduanya. Perspektif ini sangat penting untuk dipahami para pelajar yang sedang belajar dan berpikir kritis. Dalam konteks pendidikan dan pergerakan pelajar, warisan Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa intelektualitas yang sejati adalah intelektualitas yang berdampingan dengan spiritualitas. Ilmu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana menuju kedekatan dengan Allah.
IPM dalam Kaderisasi Intelektual, Moral, dan Spiritual
Dalam lanskap keorganisasian Islam di Indonesia, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) hadir sebagai wadah kaderisasi pelajar yang tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk integritas moral dan spiritualitas. Semangat ini sejatinya memiliki korelasi dengan gagasan Imam Al-Ghazali. Jika beliau menekankan keseimbangan antara hukum, akal, dan hati, maka IPM menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal.
IPM tidak ingin melahirkan pelajar yang hanya unggul secara akademik tetapi miskin akhlak, atau sebaliknya, hanya religius dalam ibadah ritual tanpa kontribusi nyata pada masyarakat. Gerakan pelajar ini ingin membentuk sosok “pelajar berkemajuan”, yakni pelajar yang kritis, religius, dan peka terhadap problem sosial di sekitarnya. Maka organisasi ini memposisikan dirinya bukan hanya sebagai ruang perkumpulan semata, melainkan juga sebagai kawah candradimuka pembentukan insan paripurna.
Korelasi antara pemikiran Imam Al-Ghazali dan gerakan IPM tampak dalam tiga ranah utama. Pertama dalam kesadaran hukum, sebagaimana Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya syariat sebagai pedoman hidup, dan IPM juga berkomitmen menumbuhkan kesadaran hukum tidak hanya dalam hukum Islam, tetapi juga dalam hukum nasional, agar pelajar mampu bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kedua dalam etika spiritual, jika Imam Al-Ghazali mengajarkan penyucian hati melalui tasawuf, IPM memaknainya sebagai ikhlas dalam berorganisasi, menjadikan dakwah dan advokasi pelajar sebagai bentuk ibadah, serta menghindarkan diri dari sikap hedonis atau pragmatis. Ketiga dalam sikap kritis dan progresif, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengakui peran akal dalam memahami dalil syariat, IPM mendorong kadernya untuk berpikir kritis, analitis, dan inovatif, namun tetap berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Maka IPM tidak hanya mewarisi semangat pembaruan Muhammadiyah, tetapi juga memperkaya tradisinya dengan nilai-nilai pemikiran klasik yang relevan untuk generasi muda.
Jika ditarik benang merah, pemikiran sufistik Imam Al-Ghazali dan gerakan intelektual IPM sama-sama menekankan keseimbangan dalam beragama dan berilmu. Imam Al-Ghazali mengingatkan pentingnya menyelaraskan syariat, akal, dan hati, sementara IPM menggemakan pentingnya keseimbangan ilmu, iman, dan amal. Keduanya sama-sama menghindari ekstremitas yang tidak jatuh pada rasionalisme kering yang mengabaikan wahyu, dan tidak pula terjebak dalam ritualisme kosong yang menafikan peran intelektualitas.
Melalui pemahaman yang diilhami oleh Imam Al-Ghazali, IPM dapat terus mengokohkan posisinya sebagai organisasi pelajar yang mencetak kader intelektual sekaligus spiritual. Pelajar Muhammadiyah tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial, integritas moral, serta spiritualitas yang kokoh. Dengan adanya pemikiran yang kuat, mereka siap menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah, memimpin perubahan, serta mengabdikan dirinya untuk umat dan bangsa. Pada akhirnya, warisan Imam Al-Ghazali bukan sekadar untuk dikenang dalam sejarah pemikiran Islam, melainkan untuk dihidupkan kembali dalam praksis organisasi pelajar, sehingga melahirkan generasi Muslim yang cerdas akalnya, bersih hatinya, dan teguh amalnya.