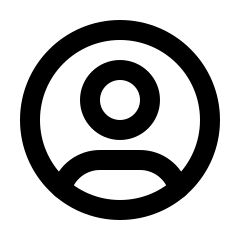Mengkritik (Pemeluk) Agama
Oleh : Ahsan Jamet Hamidi – Ketua PRM Muhammadiyah Legoso – Tangerang Selatan
Komedian Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Dalam konten lawakannya, Pandji mengkritik para politisi yang gemar memamerkan aktivitas salat di ruang publik, untuk meraih simpati. Pandji mempertanyakan apakah tindakan tersebut—yakni salat yang dipertontonkan—dapat menjamin kebaikan perilaku seorang politisi. Kurang lebih demikianlah maksud kritik yang disampaikannya. Namun demikian, hal ini masih sebatas laporan. Adapun kelanjutannya tentu dapat diikuti melalui proses hukum selanjutnya.
Saya ingin mengajak pembaca menengok peristiwa di masa lampau yang diberitakan oleh surat kabar Pemandangan pada tahun 1940. Saat itu, Soekarno yang masih muda pernah menulis tentang “Islam Sontoloyo”, sebuah kritik tajam dan menohok terhadap perilaku salah satu pemeluk agama Islam yang dinilai tidak terpuji serta bertolak belakang dengan ajaran Islam.
Sebelumnya, ada pemberitaan tentang seorang guru agama laki-laki yang mengaku tidak dapat mengajar murid-murid perempuan karena mereka bukan mahram. Secara sosial, mahram dimaknai sebagai relasi lawan jenis yang interaksinya perlu dijaga secara etis dan religius. Agar murid-murid perempuan tersebut dapat diajar, mereka diminta kesediaannya untuk dinikahi terlebih dahulu, sehingga sang guru merasa sah, halal, dan leluasa. Menurut Soekarno, perilaku guru agama tersebut merupakan bentuk tipu daya untuk mencabuli murid-murid perempuan.
Soekarno mengecam keras perilaku tersebut. Baginya, sang guru sejatinya hanya ingin menodai perempuan-perempuan yang tidak berdosa dengan dalih agama. Pelaku itu benar-benar telah mencemari agama Islam dengan mempermainkan hukum agama demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Soekarno menulis artikel berjudul Islam Sontoloyo yang dimuat di surat kabar Pemandangan pada 18 April 1940. Istilah sontoloyo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna kekonyolan, ketidakbecusan, atau kebodohan. Istilah tersebut juga ditujukan kepada para pemeluk Islam yang memandekkan perkembangan pemikiran Islam melalui penafsiran tunggal demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam praktiknya, mereka menjungkirbalikkan hukum fikih dengan mengesampingkan substansi ajaran agama.
Ada cerita lain juga tentang masa lalu yang ingin saya tulis, yaitu terkait dengan sikap Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan besar Indonesia yang dikenal lewat karya-karya realis dan kritis tentang sejarah, kolonialisme, kemanusiaan, dan ketidakadilan sosial. Saat itu, ia kerap dikritik karena keterkaitannya dengan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan karya-karyanya dinilai sekuler, tidak mencerminkan nilai ketuhanan, serta dikhawatirkan akan memengaruhi ideologi generasi muda. Buya Hamka pernah mengkritik Pramoedya, bukan terhadap karya-karya sastranya, melainkan karena posisi ideologis dan politik Pramoedya—khususnya keterlibatannya dengan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berafiliasi erat dengan PKI pada era 1950–1960-an.
Saat itu, LEKRA dikenal agresif menyerang sastrawan dan budayawan yang tidak sejalan dengan ideologi kiri, termasuk kalangan Islam. Para sastrawan di luar LEKRA, seperti H.B. Jassin, sastrawan dan kritikus sastra; Wiratmo Soekito, intelektual dan penulis; Trisno Soemardjo, sastrawan dan pemikir kebudayaan; Goenawan Mohamad, penulis dan jurnalis; serta Taufiq Ismail, penyair, akhirnya mencetuskan sikap perlawanan melalui pernyataan sikap kebudayaan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada tahun 1963.
Gerakan ini merupakan pemikiran dan sikap intelektual yang menolak penyeragaman kebudayaan oleh ideologi kiri yang diwakili LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Atas perdebatan tersebut, Pramoedya Ananta Toer kerap dianggap sebagai sosok yang anti-Islam. Benarkah demikian? Saya akan menuliskan latar belakang keluarganya.
Pramoedya Ananta Toer merupakan putra dari pasangan keluarga priyayi asal Kediri bernama Mastoer dan Siti Saidah, putri pasangan H. Ibrahim dan Siti Satimah, seorang penghulu dari keluarga santri di Rembang. Pram lahir dari lingkungan keluarga yang sangat agamis sekaligus berpendidikan. Oleh sebab itu, Pramoedya kecil sering dipanggil Gus, mengingat H. Ibrahim adalah seorang penghulu pada zaman Belanda sehingga bisa menjadi priyayi-santri yang kaya raya, hedonis, dan poligamis ulung. Ia juga dikenal sebagai “raja kecil” yang kesenangannya mengoleksi perempuan untuk dipoligami. Kakek Pram terkenal sebagai maniak perempuan yang nafsu kebinatangannya dianggap tidak terkendali (Pramoedya, 2006: 6)
Nenek Pram, Satimah, merupakan korban dari perilaku buruk kakeknya. Ia dibuang begitu saja setelah melahirkan bayi perempuan bernama Siti Saidah (ibu kandung Pram). Hidupnya hancur akibat diperlakukan secara hina oleh sosok “binatang” tua yang dikenal sebagai priyayi, santri, dan ahli agama tersebut. Karena watak bejat kakeknya yang priyayi-santri ini, Pramoedya tumbuh menjadi pribadi yang selalu bersikap kritis terhadap kaum santri dan priyayi-santri. Dalam hal beragama, Pram lebih memilih “Islam abangan” ketimbang “Islam santri” (Muhibbuddin, Pikiran-Pikiran Magis Pramoedya Ananta Toer, hlm. 17).
Merawat Kemerdekaan dalam Mengkritik
Sikap kritis komika Pandji, Soekarno, dan Pramoedya terhadap perilaku para pemeluk agama, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bukti bahwa selalu terdapat pembedaan yang tegas antara keluhuran nilai-nilai agama yang tertulis secara jelas dalam kitab-kitab suci dan perilaku para pemeluk agama itu sendiri. Ajaran agama pada dasarnya identik dengan keluhuran budi, kebaikan perilaku, kebijaksanaan sikap, kepasrahan jiwa, kecintaan, serta kasih sayang yang tulus kepada sesama makhluk Tuhan.
Dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua ajaran yang baik, luhur, dan sarat kebajikan secara otomatis terwujud secara identik dalam perilaku para pemeluk agama. Bahkan, sering kali terdapat jurang yang sangat tajam sehingga perilaku para pemeluk agama justru bertolak belakang dengan ajaran yang dianutnya. Jika ajaran agama dipahami sebagai sesuatu yang identik dengan kebaikan, maka perilaku orang beragama dapat sangat beragam: ada yang telah selaras, ada yang masih berupaya menyelaraskan diri, dan ada pula yang justru bertentangan, bahkan sangat berlawanan dengan ajaran dan prinsip agama yang dianutnya. Jika ada sikap kritis, hal itu ditujukan kepada individu pemeluk agama, bukan kepada ajaran agamanya.
Menurut hemat saya, sebagai individu yang menganut agama, seseorang memiliki kemerdekaan untuk mengkritik, mengingatkan, terlebih menasihati agar orang lain bisa berperilaku baik, penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah di muka bumi sebagai wujud dari upaya menjalankan perintah agama. Bukankah tujuan diturunkan agama adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih maslahat, damai, dan aman?
Sikap peduli yang diwujudkan melalui kritik merupakan cerminan praktik baik dari ajaran dan nilai-nilai luhur agama yang berorientasi pada kemaslahatan. Mengingat bahwa agama merupakan sumber berbagai kebaikan dalam membentuk pranata kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, agama tidak seharusnya dijadikan alasan pertikaian dan medium pertarungan di antara para penganutnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka para pemeluk agama sesungguhnya telah menjauhkan agamanya sendiri dari tujuan luhur agama. Agama menjadi cahaya justru ketika pemeluknya berani dikoreksi.