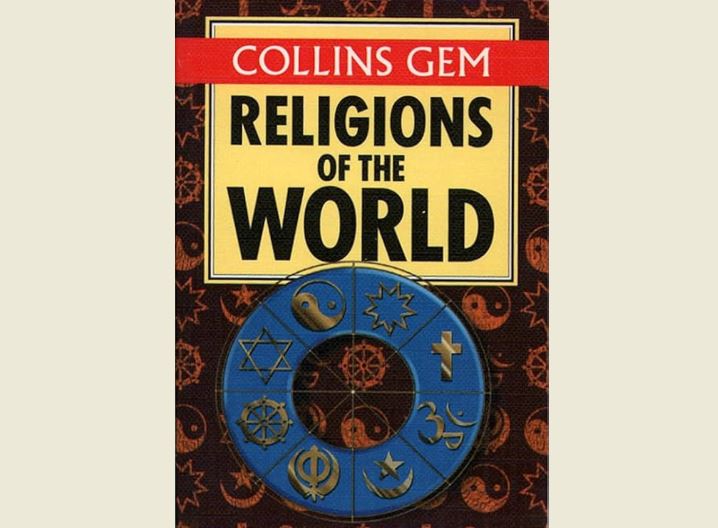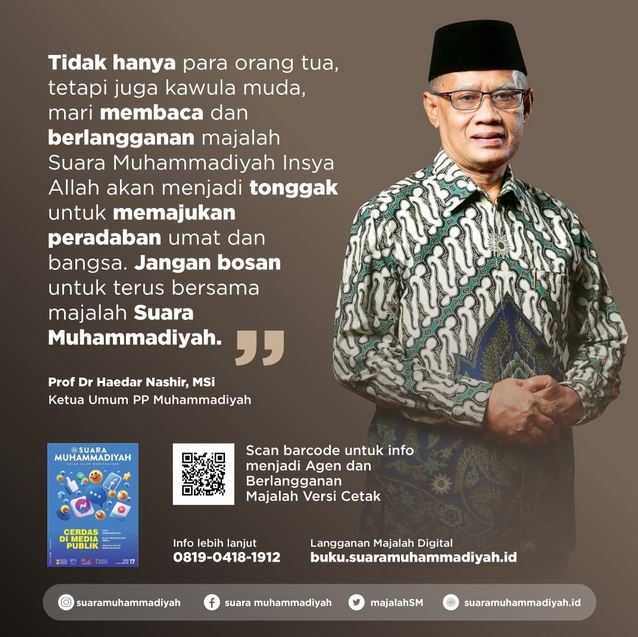PR dan Manajemen Komunikasi Krisis
Oleh: Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., Dosen Hukum dan Etika Profesi Komunikasi, FISIP, UHAMKA
Kasus antara Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, dengan seorang siswanya yang berinisial ILP (17 tahun) menjadi viral di media sosial dan memantik perdebatan luas di masyarakat. Video dan narasi yang beredar menampilkan potongan peristiwa di mana kepala sekolah menegur, dan memukul siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Dalam hitungan jam, publik menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan oleh pendidik terhadap anak.
Tak butuh waktu lama, pemberitaan media massa menggemakan peristiwa ini, membingkai konflik pendidikan tersebut bukan sebagai upaya penegakan disiplin, tetapi sebagai kasus pelanggaran hukum dan etika profesi. Framing ini menciptakan bias persepsi publik: kepala sekolah ditempatkan sebagai pelaku kekerasan, sementara konteks penegakan aturan kawasan tanpa rokok di sekolah hampir tak mendapat ruang penjelasan.
Dalam studi komunikasi, fenomena ini dikenal sebagai framing effect, yaitu cara media memilih sudut pandang tertentu dalam menyajikan fakta yang kemudian membentuk cara publik menafsirkan realitas. Dalam kasus Cimarga, framing “guru memukul murid” jauh lebih kuat dibanding framing “kepala sekolah menegakkan aturan kawasan tanpa rokok”. Padahal, keduanya merupakan bagian dari satu peristiwa yang sama.
Ketika media memilih narasi kekerasan, emosi publik yang muncul adalah simpati terhadap korban dan kecaman terhadap pelaku. Sebaliknya, jika narasinya adalah tentang disiplin dan pendidikan karakter, publik mungkin akan melihat peristiwa ini sebagai dilema moral yang kompleks. Inilah kekuatan framing dalam membentuk persepsi sosial: ia bukan sekadar menceritakan peristiwa, tetapi menentukan makna yang dilekatkan pada peristiwa itu.
Namun tanggung jawab membangun persepsi publik tidak hanya ada pada media. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola komunikasi krisis. Krisis, dalam konteks ini, bukan hanya peristiwa yang merusak reputasi, tetapi juga momen di mana kepercayaan publik terhadap lembaga diuji.
Sayangnya, dalam kasus SMAN 1 Cimarga, tidak ada komunikasi institusional yang cepat, empatik, dan komprehensif. Tidak ada pernyataan resmi yang menjelaskan konteks kejadian, dasar hukum tindakan kepala sekolah, atau langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan. Kekosongan komunikasi inilah yang kemudian diisi oleh narasi publik—yang sering kali bersumber dari potongan video, opini spontan, dan asumsi emosional. Akibatnya, sekolah tampak bersalah bahkan sebelum proses hukum dan etik dilakukan.
Dalam manajemen komunikasi krisis, terdapat prinsip yang disebut the golden hour of crisis — masa krusial dalam 24 jam pertama setelah peristiwa mencuat ke publik. Pada masa inilah institusi harus hadir memberikan klarifikasi, bukan defensif tetapi informatif dan empatik. Lembaga pendidikan, sebagai organisasi publik, seharusnya memiliki protokol komunikasi yang memastikan bahwa setiap peristiwa yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif dapat dijelaskan secara proporsional.
Dalam kasus Cimarga, misalnya, pihak sekolah atau dinas pendidikan bisa segera menyampaikan penjelasan bahwa tindakan kepala sekolah memang berawal dari penegakan aturan, namun diakui terdapat kekeliruan dalam cara penyampaiannya. Sikap terbuka semacam ini tidak hanya menenangkan publik, tetapi juga memperlihatkan tanggung jawab moral lembaga terhadap masyarakat.
Selain itu, dimensi komunikasi empatik menjadi aspek penting yang sering diabaikan dalam krisis lembaga pendidikan. Dalam situasi sensitif seperti ini, publik tidak hanya menuntut fakta, tetapi juga rasa kemanusiaan. Pernyataan yang menonjolkan empati terhadap siswa, permintaan maaf tanpa kehilangan wibawa, dan komitmen untuk memperbaiki sistem menjadi sinyal kuat bahwa lembaga masih memiliki integritas moral.
Pendekatan defensif seperti “guru juga manusia” atau “murid memang salah duluan” hanya memperpanjang ketegangan publik dan memperburuk citra lembaga. Di era digital, komunikasi bukan lagi sekadar penyampaian pesan, tetapi juga pembentukan kepercayaan (trust building) yang menjadi modal sosial utama bagi institusi pendidikan.
Lebih jauh lagi, kasus Cimarga juga menunjukkan lemahnya literasi komunikasi digital di lingkungan pendidikan. Dalam masyarakat yang sangat terhubung secara daring, setiap tindakan pendidik dapat menjadi bahan konsumsi publik dalam hitungan detik. Video amatir, potongan percakapan, hingga komentar netizen bisa menggiring opini tanpa konteks.
Karena itu, lembaga pendidikan tidak bisa lagi memandang komunikasi sebagai urusan sekunder. Diperlukan pelatihan reguler bagi kepala sekolah dan guru tentang etika komunikasi publik, penanganan konflik di era digital, serta cara menghadapi eksposur media secara profesional. Dunia pendidikan perlu beradaptasi dengan ekologi komunikasi baru, di mana transparansi, kecepatan, dan empati menjadi mata uang reputasi.
Kasus ini juga memberi pelajaran berharga tentang pentingnya kolaborasi antara hukum dan komunikasi. Hukum pendidikan memberi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pendidik, sedangkan etika komunikasi memberi panduan bagaimana hal itu disampaikan. Dalam situasi krisis, kedua aspek ini harus berjalan beriringan. Tanpa komunikasi yang baik, tindakan hukum yang benar pun bisa tampak salah di mata publik. Sebaliknya, komunikasi yang baik tanpa dasar hukum yang kuat akan terlihat manipulatif. Integrasi keduanya membentuk tata kelola lembaga pendidikan yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga beradab secara moral.
Akhirnya, peristiwa di SMAN 1 Cimarga mengingatkan bahwa reputasi lembaga pendidikan tidak hanya dibangun oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh cara lembaga itu berkomunikasi di tengah krisis. Ketika disiplin dibingkai sebagai kekerasan, dan otoritas pendidikan direduksi menjadi otoritarianisme, yang sesungguhnya gagal bukan hanya individu, melainkan sistem komunikasi yang tidak adaptif terhadap nilai-nilai publik modern.
Karena itu, sudah saatnya lembaga pendidikan di Indonesia memperkuat kapasitas komunikasi krisisnya—bukan untuk membela diri, tetapi untuk menjaga martabat pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Dunia pendidikan tidak boleh kalah oleh narasi media; ia harus mampu berbicara dengan jernih, empatik, dan bertanggung jawab, agar setiap peristiwa tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga pelajaran moral bagi semua pihak.