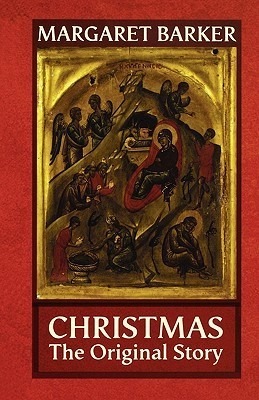Ramadhan dan Kedewasaan Umat: Merawat Damai di Tengah Perbedaan
Oleh: Syahnanto Noerdin, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI Pusat) 2021–2026 dan Alumni Mikom Fisip UMJ
Setiap kali Ramadhan tiba, umat Islam di Indonesia tidak hanya bersiap menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bersiap menghadapi satu hal yang nyaris rutin terjadi: perbedaan penetapan awal puasa. Perbedaan antara metode rukyat dan hisab kembali menjadi perbincangan, bahkan kadang memicu perdebatan yang meluas hingga ruang keluarga dan media sosial.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Ia telah berlangsung selama puluhan tahun dan berakar pada tradisi keilmuan Islam yang panjang. Namun yang menarik, perdebatan tentang perbedaan itu sering kali lebih gaduh daripada substansi ibadah yang hendak dijalankan.
Pertanyaannya bukan lagi mengapa terjadi perbedaan. Jawaban ilmiah dan fikihnya sudah jelas: dua pendekatan tersebut memiliki dasar argumentasi, metodologi, dan legitimasi keagamaan masing-masing. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya sebagai umat.
Diskursus rukyat dan hisab telah dibahas para ulama klasik sejak berabad-abad lalu. Perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika ijtihad. Bahkan di dunia Islam sendiri, tidak semua negara memulai Ramadhan pada hari yang sama. Artinya, keragaman ini bukan anomali, melainkan realitas dalam tradisi keilmuan Islam.
Keduanya lahir dari niat yang sama: menjalankan syariat dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Maka menjadikan perbedaan metode sebagai alasan untuk saling menyalahkan justru bertentangan dengan semangat keilmuan itu sendiri.
Dalam sejarah Islam, ikhtilaf tidak pernah dimaksudkan untuk memecah belah. Ia adalah konsekuensi dari keluasan ilmu dan perbedaan pendekatan dalam memahami dalil. Yang bermasalah bukanlah perbedaannya, melainkan cara kita meresponsnya.
Toleransi yang Diuji dari Dalam
Indonesia kerap membanggakan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi toleransi antaragama. Kita terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan dan tradisi. Namun ironi muncul ketika toleransi intra-agama justru terasa lebih rapuh.
Mengapa kita bisa menghormati perayaan agama lain, tetapi sulit menerima perbedaan teknis di antara sesama Muslim?
Toleransi sejati tidak berhenti pada slogan. Ia diuji justru ketika perbedaan terjadi di dalam rumah sendiri. Ketika seorang tetangga memulai puasa lebih dahulu atau lebih lambat, respons terbaik bukanlah sinisme, melainkan penghormatan.
Ramadhan seharusnya menjadi ruang pembelajaran kedewasaan spiritual, bukan ajang mempertajam ego kolektif.
Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah latihan pengendalian diri secara utuh: menahan amarah, menjaga lisan, dan mengikis rasa merasa paling benar. Dalam konteks perbedaan penetapan Ramadhan, ujian terbesarnya adalah kemampuan menahan ego kelompok.
Kedewasaan beragama terlihat bukan ketika semua seragam, melainkan ketika perbedaan tidak merusak persaudaraan.
Bayangkan jika setiap orang mampu berkata dengan tulus, “Silakan berpuasa hari ini, semoga lancar. Kami memulai besok, semoga sama-sama diberkahi.” Kesederhanaan sikap seperti itu jauh lebih mencerminkan kematangan iman daripada perdebatan panjang yang tidak produktif.
Upaya pemerintah melalui sidang isbat merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menghadirkan kepastian bagi masyarakat. Namun yang lebih penting dari keputusan teknis adalah narasi yang terus dibangun oleh para tokoh agama.
Mimbar-mimbar dakwah memiliki daya pengaruh besar. Ketika para pemuka agama menegaskan bahwa perbedaan metode adalah bagian sah dari khazanah Islam, masyarakat akan belajar memandangnya sebagai rahmat, bukan ancaman.
Energi umat tidak lagi habis untuk memperdebatkan tanggal, tetapi difokuskan pada kualitas ibadah dan penguatan solidaritas sosial.
Toleransi sering kali masih menyisakan jarak. Kita “membiarkan” yang berbeda ada. Namun Ramadhan mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi: ukhuwah. Persaudaraan yang melampaui sekadar menerima, tetapi juga menghargai dengan tulus.
Perbedaan awal dan akhir Ramadhan seharusnya menjadi cermin betapa kayanya tradisi intelektual kita. Ia adalah peluang untuk menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia mampu dewasa dalam keberagaman.
Pada akhirnya, Ramadhan bukan tentang siapa yang lebih dahulu memulai, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga hatinya tetap bersih di tengah perbedaan. Kita boleh berbeda metode, tetapi tidak boleh berbeda dalam komitmen menjaga persaudaraan.
Jika kedewasaan ini tumbuh, maka perbedaan tidak lagi menjadi jurang pemisah, melainkan jembatan yang menguatkan. Ramadhan akan benar-benar menjadi bulan penuh berkah ketika ia menghadirkan kedamaian, bukan hanya di langit penanggalan, tetapi juga di hati setiap insan. Dan di situlah ujian toleransi kita menemukan makna yang sesungguhnya. (***)