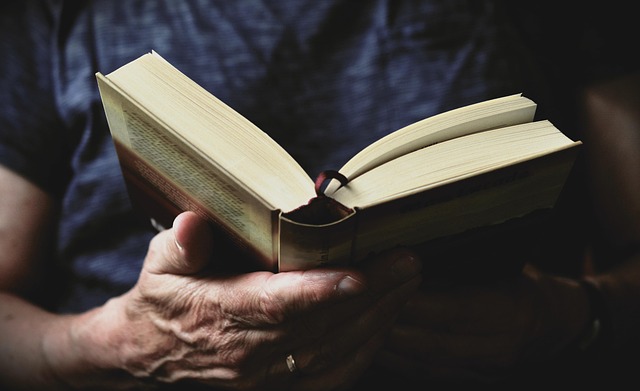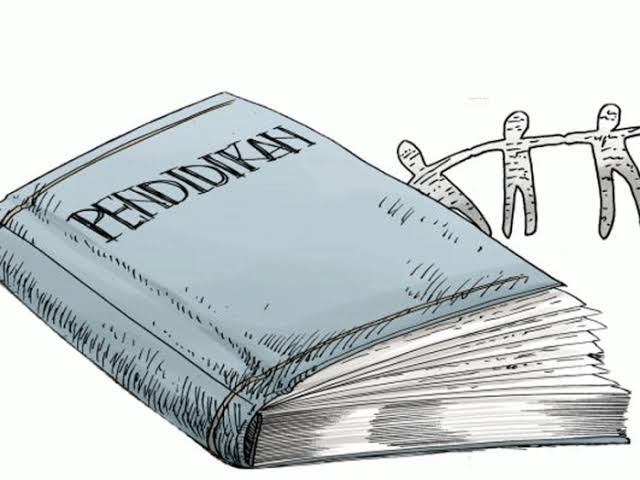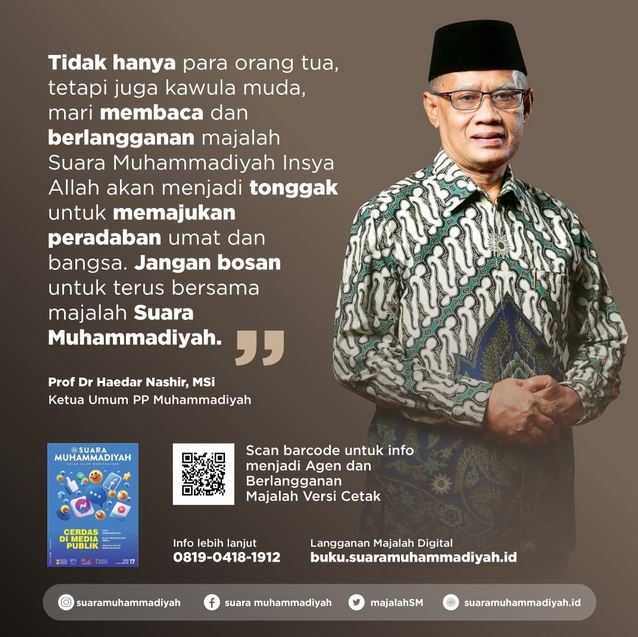Universitas Menjadi Korporasi: Antara Otonomi, Pasar, dan Integritas Ilmu
Oleh: Sobirin Malian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Di Indonesia, perguruan tinggi negeri (PTN) tengah menghadapi perubahan paradigma signifikan. Universitas yang dulu dikenal sebagai rumah ilmu, tempat pergulatan intelektual dan pengembangan kebajikan, kini mulai menampilkan wajah baru: korporasi terbuka yang berorientasi pada uang dan pasar. Transformasi ini bukan tanpa alasan, melainkan serangkaian konsekuensi dari tuntutan globalisasi, otonomi kampus, dan tekanan pasar akademik internasional.
Dulu, universitas negeri menjadi benteng utama bagi pengembangan ilmu dan tempat lahirnya pemikiran kritis tanpa batas intervensi bisnis. Kini, rektor sering bicara layaknya CEO perusahaan, sedangkan dekan berhadapan seperti manajer unit bisnis. Para dosen pun sibuk mengajukan proposal penelitian bernilai komersial demi mendapatkan insentif, bukan semata-mata demi mengembangkan pengetahuan yang bermakna bagi masyarakat.
Mahasiswa tidak lagi dianggap sebagai pencari ilmu yang aktif dan kritis, melainkan “stakeholder utama” dalam bisnis pendidikan. Tri Dharma perguruan tinggi, yang sejatinya berisi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, perlahan berubah menjadi Tri Target: publikasi demi skor, peringkat demi reputasi, dan pendapatan demi kelangsungan bisnis kampus. Ini adalah tanda bahwa pendidikan tinggi mulai mengadopsi mekanisme pasar yang seharusnya tidak menguasai jiwa akademik.
Filsuf dan pendidik legendaris seperti Socrates memberikan pelajaran berharga bahwa pencapaian utama pendidikan adalah menyalakan api berpikir, bukan sekadar mengisi bejana dengan informasi. Socrates berdialog di pasar — bukan dalam rangka mengejar kuantitas publikasi atau peringkat internasional. Namun, di banyak universitas negeri saat ini, api berpikir tersebut terasa kian padam di bawah tumpukan laporan penelitian, pemujaan terhadap indeks sitasi, dan rapat kinerja yang tiada henti.
Pada banyak kampus, waktu dan tenaga akademisi lebih banyak tersita untuk memenuhi target administratif dan kuantitatif, sementara momen diskusi terbuka tentang ilmu dan kebajikan semakin langka. Ini menjadi paradoks sebuah institusi yang diciptakan untuk mengembangkan jiwa dan nalar manusia.
Ironi dan Realita terhadap Ranking Global
Peringkat global seperti QS World University Rankings dan Times Higher Education memang membawa standar internasional yang diidamkan banyak perguruan tinggi. Tapi secara filosofis dan struktural, ranking tersebut lebih relevan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) yang betul-betul hidup dari persaingan pasar pendidikan tinggi. PTS membutuhkan visibility, promosi, dan daya tarik untuk merekrut mahasiswa agar bisa bertahan dalam pasar kompetitif.
Di lain pihak, PTN mendapat beban berbeda karena mereka merupakan lembaga yang didanai oleh negara dan diamanahkan untuk mencetak sumber daya manusia terbaik dari berbagai lapisan masyarakat, terutama lulusan SMA unggulan. Namun, kini banyak kampus negeri yang ikut berlomba mengejar ranking, melakukan promosi internasional, dan memaketkan diri sebagai “World Class University,” seolah universitas harus beriklan seperti produk komersial.
Realitas ini memperlihatkan ketegangan antara tugas pendidikan publik dengan logika pasar global yang menuntut kuantitas dan visibilitas lebih dari substansi dan manfaat sosial. Risiko yang muncul adalah kampus negeri mengalihkan fokusnya dari pelayanan publik menjadi permainan bisnis yang mengutamakan popularitas.
Al-Farabi dan Madīnah al-Fāḍilah versus Madīnah al-Korporāt
Filsuf klasik al-Farabi mencita-citakan kota ideal atau al-madīnah al-fāḍilah, di mana ilmu bertujuan menghadirkan kebajikan dan kemanfaatan bagi seluruh warga. Namun, perguruan tinggi negeri hari ini justru bergerak menuju madīnah al-korporāt — kota akademik yang bergantung pada dua sumber dana, yakni dana APBN dari rakyat dan dana swakelola atau komersialisasi. Dalam hal ini, perguruan tinggi negeri seperti memegang dua “sumber napas” yang memberi mereka keunggulan finansial.
Sementara itu, perguruan tinggi swasta harus mengandalkan UKT mahasiswa dan donasi yang makin terbatas untuk bertahan. Keadaan ini menghasilkan ketimpangan daya saing yang nyata, dengan PTN-BH berjalan seperti pelari yang memakai sepatu terbaik, sementara PTS berlari dengan tanpa alas kaki di medan yang sama. Dalam posisi demikian, kebijakan atau regulasi yang terukur dan jelas semestinya dimiliki oleh pemerintah untuk mengatasinya.
Terlepas dari otonomi bisnis yang diklaim memberikan fleksibilitas bagi PTN-BH, ketidaksetaraan pendanaan dan dukungan negara ini menimbulkan perasaan tidak adil bagi PTS yang juga ingin berkontribusi dan bersaing secara global. PTS sudah melakukan berbagai inovasi dan kerja keras dengan sumber daya terbatas, mulai dari membuka program studi ganda, menjalin kolaborasi internasional, hingga inovasi pembelajaran digital. Mereka menciptakan ruang pengembangan ilmu sekalipun tanpa fasilitas megah.
Ironisnya, media dan kebijakan masih lebih menyoroti keberhasilan PTN yang menaikkan peringkat internasional. Keberhasilan ini pun terkadang dipertanyakan karena didukung oleh dua sumber pendanaan dan fasilitas yang jauh melampaui kampus swasta.
Dalam pusaran kompetisi dan komersialisasi akademik ini, suara-suara akademisi yang mendambakan ilmu sebagai ladang kebenaran dan kebajikan mulai tersamar. Jika Socrates masih hidup atau Ahmad Dahlan masih ada, barangkali ia akan mengkritik keras sistem akademik yang membuat muridnya berlomba-lomba menulis untuk insentif, bukan demi mencari kebenaran abadi.
Al-Farabi pun barangkali akan menulis ulang kitabnya, menegaskan pentingnya kebajikan dalam era Scopus dan peringkat dunia. Ia akan mengingatkan bahwa ilmu tanpa integritas dan keadilan sosial hanyalah investasi sesaat yang rapuh.
Menjaga Integritas dan Kesempatan yang Adil
Pemerintah dan institusi kampus negeri perlu menyadari bahwa pemberian otonomi harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga integritas akademik dan keadilan kesempatan. Otonomi yang memberi ruang bagi perguruan tinggi negeri untuk mengelola bisnis tidak boleh menghilangkan sumber utama nilai keilmuan, yakni integritas dan kontribusi sosial.
Universitas harus kembali menjadi laboratorium pikiran yang berisi cahaya — bukan tempat investasi jangka pendek dalam bursa reputasi dunia. Pendidikan tinggi sejatinya adalah misi panjang untuk menyalakan api ilmu, menumbuhkan kebajikan masyarakat, dan membangun masa depan bangsa yang berkeadilan.
Bagaimana pun, universitas negeri yang kini bertransformasi menjadi korporasi semata-mata menjadi “momok” bagi perguruan tinggi swasta. Kendati disadari juga kebutuhan akan dana juga mutlak penting. Hal yang paling esensial, jangan sampai kesan “perlombaan” ini berpotensi menafikan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pertama, otonomi yang memberikan fleksibilitas pada universitas memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas riset dan pengajaran jika dikelola dengan baik, karena adanya dorongan untuk inovasi dan pencapaian hasil yang nyata.
Kedua, orientasi terhadap pasar dan standar global dapat memacu perguruan tinggi untuk mengadopsi praktek terbaik internasional dalam tata kelola, kurikulum, dan fasilitas. Dengan demikian, lulusan universitas negeri bisa lebih kompetitif dan siap bersaing di kancah global, sehingga mendorong peningkatan mutu pendidikan.
Namun, jika orientasi korporasi hanya menonjolkan aspek komersial tanpa menjaga integritas akademik dan misi sosial pendidikan, maka kualitas pendidikan berisiko menurun. Fokus hanya pada peringkat atau jumlah publikasi, tanpa memperhatikan makna dan dampak sosial, akan melemahkan pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter, pemikiran kritis, dan kebajikan.
Hal yang ideal adalah keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas, antara orientasi bisnis dan misi sosial dapat terjaga. Universitas negeri perlu menjaga akar pendidikan yang membebaskan, mendidik dengan integritas dan hati nurani, sambil tetap mampu beradaptasi dengan dinamika dunia modern dan persaingan global.
Jadi, meskipun transformasi menuju model korporasi bisa membawa manfaat dalam pengelolaan dan daya saing, mengabaikan aspek nilai-nilai akademik dan pendidikan yang sejati dapat menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pandangan kritis penting digunakan sebagai pengingat agar keberhasilan bisnis tidak mengorbankan esensi pendidikan. Hal ini berlaku juga pada perguruang swasta.