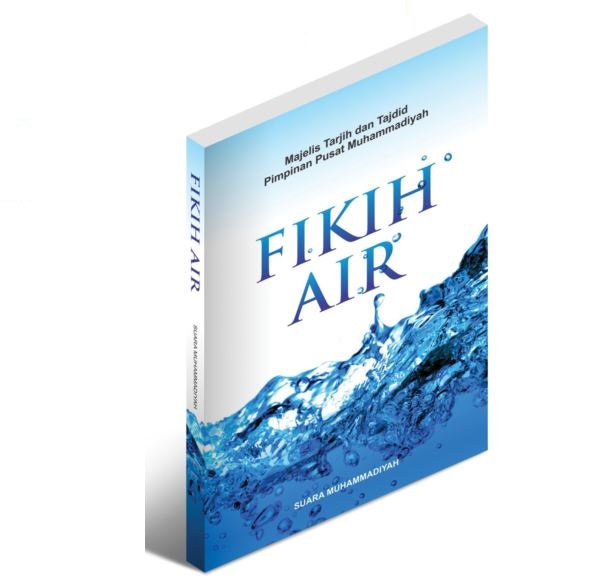Etika Ekologis dalam Ibadah Ramadhan
Oleh : Gufron Amirullah, Dosen Uhamka, Wakil Sekretaris Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah
Pada Bulan Ramadhan 1447 H, diskursus keagamaan dihadapkan pada tantangan global yang menuntut reposisi peran manusia sebagai khalifah—manajer ekologis yang memegang mandat atas keberlangsungan semesta. Di tengah dinamika krisis iklim yang kian eskalatif, ibadah puasa tidak lagi dapat dipandang sebagai ritual privat semata. Muncul urgensi untuk mengarusutamakan etika ekologis dalam beribadah, sebuah gerakan yang menuntut audit perilaku konsumsi guna menekan laju degradasi lingkungan. Krisis ekologi saat ini merupakan validasi empiris atas peringatan dalam Surah Ar-Rum ayat 41 mengenai kerusakan sistemik di darat dan laut akibat intervensi manusia yang destruktif. Melalui kacamata ilmiah populer, narasi menuju Green Ramadhan ini harus diiringi dengan kesadaran menjaga alam sebagai bagian integral dari ketakwaan.
Namun, mandat suci untuk menjaga bumi tersebut sering kali terbentur pada realitas perilaku kita di meja makan. Anomali perilaku konsumsi selama bulan suci sering kali menghadirkan paradoks pangan yang memprihatinkan. Berdasarkan data, volume sampah nasional pada tahun 2026 diproyeksikan menyentuh angka 12,4 juta ton, di mana porsi terbesarnya (57%) berasal dari sampah makanan. Untuk memberikan gambaran visual, akumulasi limbah tahunan ini setara dengan membentuk bukit sampah setinggi Tugu Monas di atas lahan seluas 170 lapangan sepak bola.
Fenomena ini menjadi ironi kemanusiaan jika dikomparasikan dengan laporan terbaru PBB melalui The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI), yang mencatat sekitar 673 juta jiwa masih terjebak dalam krisis pangan akut secara global. Ketimpangan sistemik ini merupakan kontradiksi nyata terhadap target Sustainable Development Goals (SDGs) mengenai konsumsi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Green Ramadhan bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan keharusan etis untuk menghentikan "sampah moral" yang dihasilkan dari ketidakbijaksanaan kita dalam mengelola konsumsi.
Fondasi teologis dari kesadaran ini berakar pada konsep tauhid dan keseimbangan ekologis. Dalam studi komparatif ekotafsir terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan Hamka, dijelaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam kondisi seimbang (mizan). Bulan Ramadhan menjadi momentum krusial untuk mengembalikan fitrah manusia yang sering kali mengabaikan keseimbangan tersebut demi pemuasan hasrat konsumtif. Internalisasi konsep tasbih semesta (universal glorification) menjadi variabel teologis yang sangat krusial; di mana flora dan fauna dikonstruksikan sebagai komunitas makhluk hidup yang memiliki otonomi dalam ketundukan kepada Sang Pencipta. Implementasi reduksi jejak karbon dan minimalisasi limbah selama bulan suci merupakan manifestasi konkret dari etika altruisme terhadap entitas biotik lainnya, memastikan bahwa "resonansi spiritual" alam semesta tidak terganggu oleh eksploitasi antropogenik.
Secara psikologis, pengendalian diri dalam Ramadhan berkaitan erat dengan praktik asketisme religius. Asketisme dipahami sebagai gaya hidup yang membatasi pemenuhan hasrat fisik guna mencapai kedalaman spiritual. Praktik ini, jika dikelola dengan konstruksi makna yang tepat, dapat menjadi faktor protektif bagi kesehatan mental dan meningkatkan fungsi regulasi diri. Dalam konteks ekologis, asketisme bertransformasi menjadi teknik pengendalian ego untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. internalisasi nilai religius yang kuat—bukan karena distorsi citra tubuh—terbukti memberikan dampak terapeutik yang signifikan, menjadikan puasa sebagai sarana penyembuhan baik bagi jiwa manusia maupun bagi bumi yang sedang sakit.
Narasi sejarah Islam pun telah memberikan keteladanan asketisme yang luhur sebagai otoritas moral atas keinginan material. Figur sahabat Rasulullah, Abu Hurairah RA yang menahan lapar ekstrem demi stabilitas spiritual, hingga praktik itsar (altruisme) Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang memprioritaskan kebutuhan sosial di atas kepentingan pribadi, adalah simbolisasi dari nilai spiritualitas tinggi. Narasi ini menegaskan bahwa keberkahan ekonomi terletak pada efisiensi dan distribusi, bukan akumulasi. Jika para pendahulu mampu menerapkan prinsip kecukupan dalam keterbatasan, merupakan kegagalan moral jika manusia modern terjebak dalam budaya buang-buang makanan di tengah degradasi bumi. Pemikiran tokoh bangsa seperti K.H. Ahmad Dahlan melalui Teologi Al-Ma'un mempertegas bahwa iman yang sejati harus berbuah pada aksi nyata menyelamatkan lingkungan.
Sebagai simpulan, esensi puasa untuk mencapai derajat takwa harus diterjemahkan menjadi pengendalian diri yang presisi terhadap lingkungan. Takwa bukan sekadar urusan metafisika privat, melainkan kesadaran ekologis bahwa setiap tindakan kita terhadap alam akan dimintai pertanggungjawabannya secara transendental. Integrasi etika ekologis dalam Ramadhan 1447 H adalah keniscayaan bagi setiap individu yang berkomitmen pada keberlangsungan peradaban. Dengan menjaga keseimbangan alam melalui prinsip Green Ramadhan, kita tidak hanya menyempurnakan ibadah secara vertikal kepada Allah, tetapi juga memenuhi mandat suci sebagai pelindung bumi demi masa depan yang aman, sehat, dan seimbang.